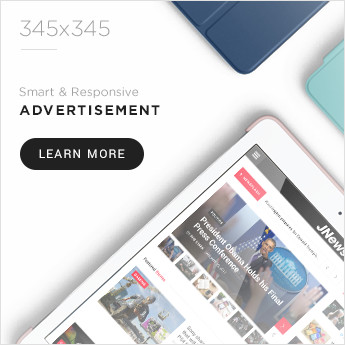Di era digital ini, agama pun ikut terkena “demam instan”. Kalau dulu orang rela duduk berjam-jam mendengar pengajian di serambi masjid, kini cukup lima menit scrolling Instagram atau TikTok, kita bisa dapat “dosis” ceramah singkat yang katanya bikin hati adem. Fenomena “ustaz cepat saji” ini merebak di mana-mana, dibungkus dengan caption yang dramatis, backsound musik sedih, dan teks tebal warna kuning. Hasilnya? Satu potongan ceramah bisa dibagikan seribu kali hanya dalam hitungan jam.
Pertanyaannya, apakah ini tanda baik atau justru gejala baru di mana agama mulai diperlakukan seperti mi instan: cepat, praktis, mengenyangkan… tapi kadang miskin gizi?
Dari Mimbar ke Layar Kecil
Dulu, mimbar masjid adalah panggung utama para ulama. Jamaah mendengar dengan khidmat, ada tanya-jawab, ada interaksi, dan ada konteks yang lengkap. Kini, panggung itu bergeser ke layar ponsel. Ustaz tak lagi butuh podium cukup tripod dan kamera ponsel. Lima menit pertama di depan kamera bisa menentukan nasib dakwahnya: viral atau tenggelam. Karena itu, tak jarang materi dakwah “dipadatkan” seperti kopi sachet. Satu tema besar, dipotong menjadi kutipan-kutipan manis yang mudah dicerna, tapi sering kali kehilangan kedalaman makna.
Seorang ustaz muda pernah berkata, “Kalau ceramah saya lebih dari 7 menit, algoritma TikTok sudah marah.” Bayangkan, di sini bukan lagi jamaah yang tak betah duduk lama, tapi mesin algoritma yang jadi “penentu waktu khutbah”.
Antara Dakwah dan Drama
Tak bisa dipungkiri, sebagian ustaz cepat saji memang punya niat tulus menyebarkan ilmu. Mereka paham generasi digital punya rentang perhatian sependek durasi iklan YouTube. Maka, dibuatlah ceramah singkat yang mudah diingat dan gampang dibagikan.
Namun, di sisi lain, ada juga yang tergoda menjadikan ceramah sebagai konten “jualan”. Bukan hanya jualan produk, tapi juga jualan citra. Kalimat-kalimat dipilih yang paling “menggigit”, meski konteksnya kadang hilang.
Kita sering melihat potongan video berisi satu-dua kalimat keras tentang neraka atau poligami yang dibagikan tanpa penjelasan lengkap. Hasilnya? Komentar membludak, debat terjadi, dan engagement naik. Algoritma senang, tapi apakah Allah pun senang?
Makanan Cepat Saji untuk Hati
Fenomena ini mengingatkan pada peringatan Imam al-Ghazali berabad-abad lalu: ibadah tanpa pemahaman hanyalah gerakan kosong. Demikian pula dakwah: kalau hanya dikonsumsi secara kilat tanpa refleksi, yang masuk ke hati hanyalah bumbu, bukan gizi utamanya.
Ceramah cepat saji ibarat burger di restoran cepat saji—mengenyangkan untuk sementara, tapi tidak memberi kekuatan jangka panjang. Sebaliknya, kajian mendalam ibarat masakan rumah yang pelan-pelan dimasak, penuh bumbu, dan memberi nutrisi yang langgeng. Masalahnya, di era ini, orang lebih memilih yang cepat. Kita ingin jadi saleh seperti mengunduh aplikasi: tinggal klik, selesai dalam hitungan menit.
Viral Bukan Berarti Benar
Sejarah Islam mencatat, ulama-ulama besar seperti Imam Malik atau Syekh Nawawi al-Bantani menulis karya yang dibaca selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ilmu mereka tak viral di TikTok, tapi mengubah peradaban.
Bandingkan dengan sekarang: sebuah video ceramah ustaz bisa tembus sejuta tayang hanya karena cara bicaranya “meledak-ledak” atau mimiknya dramatis. Apakah ini tanda keberhasilan dakwah? Belum tentu. Viral hanya berarti pesan itu populer, bukan bahwa pesan itu benar atau bermanfaat.
Bahaya dari dakwah instan ini adalah ilmunya sering lepas dari rujukan. Kutipan hadits bisa dipotong, tafsir ayat diambil sepotong, atau kisah sahabat direka-ulang agar lebih “menyentuh”. Tugas kita sebagai pendengar adalah tidak menelan mentah-mentah setiap kata yang viral.
Ketika Agama Menjadi Konten
Media sosial bekerja dengan logika pasar: yang laris, itulah yang dijual. Maka, ustaz yang ingin bertahan di dunia maya mau tak mau harus “menyesuaikan kemasan” agar menarik. Inilah titik rawan di mana agama berubah jadi “komoditas hiburan”.
Ceramah jadi seperti stand-up comedy harus mengundang tawa atau air mata dalam waktu singkat. Latar musik dipilih yang bikin merinding, teks diperbesar agar cocok di-share ke status WhatsApp. Lama-lama, agama dipersepsikan bukan sebagai jalan hidup, tapi sekadar hiburan rohani. Ustadz cepat saji mungkin tidak salah niat, tapi media sosial punya cara sendiri untuk “membentuk” gaya dakwah mereka. Yang tidak dramatis, tenggelam. Yang tidak singkat, ditinggalkan.
Kembali ke Kedalaman
Fenomena ustadz cepat saji seharusnya jadi pengingat, bukan sekadar bahan kritik. Artinya, kita perlu dua hal: para dai yang mau tetap menjaga kedalaman ilmunya meski berdakwah di media baru, dan jamaah yang mau meluangkan waktu lebih dari lima menit untuk belajar agama.
Seorang ulama besar pernah berkata, “Ilmu itu ibarat sumur. Siapa yang hanya meneguk permukaan, hanya akan mendapat air keruh.” Maka, jika kita ingin beningnya, kita harus mau menyelam lebih dalam. Kalau hati ingin benar-benar tenang, kita perlu lebih dari sekadar video lima menit. Kita perlu duduk di majelis, membaca kitab, dan berdialog langsung dengan guru. Media sosial boleh jadi pintu masuk, tapi bukan rumahnya.
Mungkin kita harus ingat, agama ini tidak diturunkan untuk dikejar algoritma, melainkan untuk menuntun hati. Jadi, lain kali saat menonton ceramah lima menit di TikTok dan merasa tersentuh, jangan berhenti di situ. Cari kelanjutannya, gali sumbernya, dan lihat apakah hati kita sekadar tersentuh… atau benar-benar berubah.
Kalau kata pepatah digital: jangan biarkan iman kita buffering di tengah jalan, hanya karena kita malas mengunduh ilmu yang utuh.