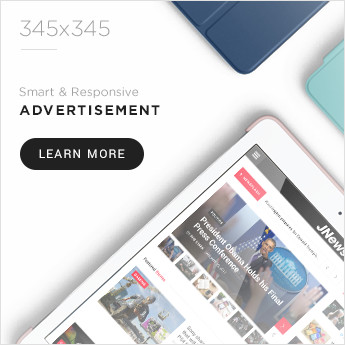Apa jadinya ketika kemiskinan bukan lagi aib, tapi dijadikan identitas resmi oleh negara? Itulah yang kini terjadi di Bengkulu. Rumah-rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) ditempeli stiker besar bertuliskan “Keluarga Miskin”, seolah-olah kemiskinan adalah status sosial yang harus diumumkan kepada public bukan kondisi yang perlu diangkat martabatnya.
Fenomena ini mengundang gelombang protes dan ironi sekaligus. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai bentuk transparansi, tapi di baliknya ada perbudakan sosial yang dilembagakan secara halus: negara membuat rakyatnya miskin, lalu memaksa mereka untuk bangga menjadi penerima belas kasihan.
Ketika Bansos Jadi Alat Kontrol, Bukan Kepedulian
Kisah ini mencuat dari Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Sebuah video memperlihatkan petugas dinas sosial menempelkan stiker “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan. Dengan nada yang terdengar tegas, petugas berkata: “Kalau menolak, silakan keluar dari daftar penerima bansos.”
Beberapa keluarga pun memilih mundur. Mereka lebih memilih lapar daripada dipermalukan. Tapi tak sedikit pula yang menerima, karena “tidak ada pilihan lain.” Di titik inilah tragedi itu lahir: ketika kemiskinan bukan lagi sesuatu yang ingin diperbaiki, tapi diterima dengan pasrah sebagai nasib dan tanda keabsahan bantuan.
Seolah-olah negara berkata: “Kami bantu kalian, tapi biarkan dunia tahu bahwa kalian memang miskin.”
Kemiskinan yang Dilembagakan
Labelisasi publik terhadap penerima bantuan bukan hal baru, tapi cara pelaksanaannya kini melampaui batas kemanusiaan. Dengan dalih transparansi, negara menempatkan rakyatnya dalam posisi paling rentan menjadi tontonan sosial. Rumah dengan stiker “Keluarga Miskin” kini tak ubahnya museum penderitaan: terbuka, terlihat, dan dijadikan pembenaran atas statistik keberhasilan program sosial.
Masalahnya, ketika kemiskinan dipajang, ia berhenti menjadi masalah yang harus diselesaikan. Ia berubah menjadi sistem yang justru dipelihara. Karena tanpa rakyat miskin, tak ada yang bisa dijadikan data keberhasilan penyaluran bansos.
Dari Bantuan Jadi Budaya Ketergantungan
Inilah bentuk modern dari perbudakan sosial. Kita hidup di era di mana bantuan bukan lagi jalan keluar, tapi candu politik. Labelisasi “Keluarga Miskin” hanyalah wajah baru dari politik ketergantungan yang halus.
Negara hadir bukan untuk memberdayakan, tetapi untuk mengontrol. Rakyat dipaksa memilih: mau bantuan, maka terima labelnya. Menolak label, maka siaplah miskin tanpa belas kasihan.
Dalam psikologi sosial, ini disebut learned helplessness ketidakberdayaan yang dipelajari. Masyarakat diajarkan untuk menerima statusnya sebagai miskin, merasa berterima kasih ketika diberi sedikit, dan diam ketika dihina lewat sistem yang mereka tidak kuasai.
Ironi Transparansi: Ketika Pengawasan Berubah Jadi Penghinaan
Pemerintah beralasan bahwa pemasangan stiker bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tapi pertanyaan sederhana: apakah kemanusiaan bisa diganti dengan efisiensi? Apakah harga diri harus dikorbankan demi data yang rapi?
Yang lebih tragis, kebijakan ini dijalankan dengan persetujuan dua belah pihak. Artinya, rakyat kini rela dilabeli demi mendapatkan bantuan. Di sinilah ironi paling kelam itu muncul: kemiskinan dijadikan kesepakatan sosial yang dilegalkan.
Kita sedang menyaksikan bentuk baru kolonialisme bukan oleh bangsa asing, tapi oleh sistem kebijakan sendiri. Jika dulu dijajah karena tanah dan tenaga, kini dijajah lewat data dan stiker.
Bansos dan Kebanggaan Palsu
Label “Keluarga Miskin” tidak hanya menandai siapa yang menerima bantuan, tapi juga menciptakan kebanggaan palsu. Seolah-olah menjadi miskin dan menerima bantuan adalah bentuk “hubungan baik” dengan pemerintah.
Inilah bentuk propaganda yang halus. Bansos bukan lagi wujud empati sosial, tapi alat legitimasi politik. Siapa yang patuh dan diam, akan terus diberi. Siapa yang menolak label atau bertanya, akan dicoret. Maka jangan heran jika kemiskinan tidak pernah benar-benar berkurang, hanya berpindah wajah dari penderitaan ekonomi ke ketergantungan politik.
Krisis Martabat di Tengah Data Statistik
Secara statistik, angka kemiskinan Bengkulu memang menurun. Tapi mari jujur: apakah kemiskinan benar-benar hilang, atau hanya disamarkan lewat narasi “bantuan tersalurkan”?
Martabat manusia tak bisa diukur dengan angka. Tidak ada data yang mampu menggambarkan rasa malu seorang ayah ketika rumahnya diberi label “Keluarga Miskin”. Tidak ada laporan kinerja yang bisa menuliskan rasa perih seorang ibu ketika anaknya diejek karena stiker di dinding rumah mereka.
Bantuan yang menghina lebih kejam dari kemiskinan itu sendiri. Karena ia tidak hanya membuat orang lapar, tapi juga mencuri kehormatan.
Saat Negara Membuat Kemiskinan Jadi Identitas
Labelisasi bansos di Bengkulu adalah potret paling jujur dari wajah kesejahteraan semu di negeri ini. Ia memperlihatkan bagaimana sistem yang seharusnya membebaskan, justru menindas secara halus.
Kita hidup di era di mana kemiskinan dilegalkan, dimaklumi, bahkan dirayakan dalam bentuk stiker. Warga yang seharusnya berdaya malah diajari untuk bersyukur karena “masih diakui miskin.” Dan negara, yang seharusnya menciptakan kemandirian, justru menciptakan budaya tunduk.
Labelisasi ini bukan sekadar persoalan kebijakan. Ia adalah tanda runtuhnya peradaban, ketika kemiskinan tidak lagi dianggap masalah moral, tetapi alat politik. Dan ketika rakyat merasa bangga disebut miskin karena itu syarat menerima bantuan, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang yakni harga diri sebagai manusia.