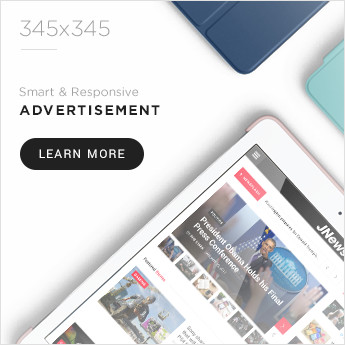Indonesia dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga karena warisan mistiknya yang begitu kental. Dari desa terpencil hingga kota besar, cerita tentang orang sakti, kiai bertapa, atau dukun penyembuh selalu punya tempat istimewa di benak masyarakat. Namun, di tengah arus modernisasi dan derasnya gelombang rasionalitas, muncul sosok muda yang mengguncang kenyamanan mistis itu: Gen Alfarizi. Anak muda ini dikenal karena keberaniannya membongkar fenomena mistik Indonesia dengan pendekatan logika, sains, dan rasionalitas.
Dan tentu saja, langkahnya tak lepas dari kontroversi terutama di kalangan “orang sakti berkopyah”, sebutan satir untuk sebagian tokoh spiritual atau religius yang dianggap masih menjual aura kesaktian dengan bungkus agama.
Dari Mistisisme ke Logika: Revolusi di Kepala Anak Muda
Gen Alfarizi bukan sekadar pembuat konten. Ia mewakili fenomena baru: generasi muda yang berani berpikir kritis di tengah masyarakat yang masih percaya hal ghaib tanpa dasar.
Dalam berbagai unggahan dan kontennya, ia menyoroti hal-hal yang sering dianggap tabu untuk dikritik: kesaktian kyai, karomah wali, jimat, bahkan praktik pengobatan alternatif yang tak rasional. Dengan gaya santai dan argumentatif, ia mengajak audiens muda berpikir: “Kalau katanya bisa menyembuhkan, mana bukti ilmiahnya?”
Inilah yang membuatnya diserang banyak pihak. Sebagian menuduhnya sombong, kurang adab, atau bahkan menista ulama. Namun, sebagian lainnya terutama generasi muda justru menemukan semangat baru: keberanian untuk berpikir logis tanpa kehilangan rasa hormat pada agama.
Di sinilah letak menariknya. Gen Alfarizi bukan ateis, bukan anti-agama, tapi ingin memurnikan akal sehat dari kabut mistisisme yang menutupi ajaran tauhid sejati.
Logika Mistika ala Tan Malaka dan Fenomena Alfarizi
Untuk memahami gerakan pemikiran seperti Gen Alfarizi, kita bisa meminjam teori Tan Malaka dalam karyanya Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika).
Tan Malaka menyebut bahwa bangsa Indonesia lama terjebak dalam cara berpikir “logika mistika” cara berpikir yang menggantungkan sebab akibat pada hal-hal gaib dan irasional. Dalam logika mistika, orang percaya penyakit disebabkan oleh roh jahat, rezeki ditentukan oleh dukun, atau keberuntungan bisa dibeli dengan jimat.
Tan Malaka menganggap cara berpikir semacam ini berbahaya karena membunuh daya nalar dan kemandirian manusia. Ia menulis:
“Selama logika mistika masih berkuasa, bangsa ini akan sulit maju, karena ia lebih percaya pada takhayul daripada pada akal.”
Gen Alfarizi seolah menghidupkan kembali semangat Madilog itu tapi dengan versi generasi Z. Bedanya, ia tidak menulis pamflet atau buku, melainkan menggunakan media digital: video, diskusi daring, dan eksperimen sosial. Ia membuktikan bahwa berpikir rasional tidak harus kaku; bisa dibungkus dengan gaya pop, sarkasme, dan humor.
Generasi Rasional vs Generasi Mistikal
Bandingkan Gen Alfarizi dengan banyak anak muda lain seumurannya.
Sebagian besar dari mereka masih percaya hal-hal mistis dengan cara lama: nonton konten horor tiap malam, takut lewat kuburan, percaya “kamar berhantu”, dan menilai sesuatu dari “aura” bukan fakta. Ironisnya, mereka sering mengaku modern, tapi masih menaruh sesajen di kos karena “takut penunggu marah”.
Sementara Alfarizi dan sebagian kecil generasi kritis justru bertanya:
“Kalau kamu percaya penunggu, berarti kamu percaya selain Allah punya kuasa dong?”
Pertanyaan seperti ini bukan bentuk penghinaan terhadap tradisi, tapi upaya mengembalikan kesadaran tauhid. Ia mengajak generasi muda untuk tidak membiarkan ketakutan spiritual menggantikan logika.
Sayangnya, keberanian semacam ini sering dianggap “kurang ajar” oleh sebagian tokoh tua. Padahal, justru dari perdebatan ini lahir kesadaran baru: bahwa iman dan akal bukan musuh, tapi sekutu.
“Orang Sakti Berkopyah” dan Politik Mistisisme
Sebagian “orang sakti berkopyah” merasa terusik.
Istilah ini tidak menunjuk individu tertentu, melainkan fenomena sosial: orang yang menggunakan simbol-simbol agama kopiah, jubah, tasbih untuk memperkuat citra kesaktian dan kewibawaan spiritual. Mereka bisa membaca nasib, menyembuhkan penyakit, atau menjanjikan rezeki, tapi dengan “syarat” tertentu.
Di masyarakat yang masih mudah kagum pada simbol religius, praktik seperti ini laku keras. Dan ketika Gen Alfarizi datang dengan logika, skeptisisme, dan data ilmiah, ia dianggap mengancam otoritas mereka.
Inilah titik paling menarik dari kontroversi itu: bukan sekadar benturan generasi, tapi benturan paradigma.
Yang satu bertahan pada tradisi karomah dan kesaktian, yang lain menuntut pembuktian rasional dan transparansi.
Apakah orang sakti berkopyah salah? Tidak selalu. Tapi ketika kesaktian dijadikan alat pengaruh sosial bahkan politik maka kritik seperti yang dilakukan Alfarizi menjadi penting sebagai koreksi moral dan intelektual.
Kritik Gen Alfarizi seharusnya tidak dibaca sebagai penghinaan terhadap agama atau ulama, tapi sebagai ajakan untuk membedakan antara spiritualitas dan mistisisme palsu.
Ia ingin mengajak generasi muda Islam untuk mempraktikkan iman yang logis bukan iman yang takut pada bayangan sendiri.
Islam sendiri, sejak masa awal, mengajarkan berpikir rasional. Al-Qur’an berulang kali mengajak manusia untuk tafakkur(berpikir) dan tadabbur (merenung). Nabi Muhammad SAW bahkan menolak praktik perdukunan dan kesaktian tanpa dasar wahyu.
Maka ketika Gen Alfarizi mengingatkan agar kita tidak lagi memuja jimat, minyak pengasihan, atau “orang sakti berkopyah”, ia sejatinya sedang mengembalikan kita pada ajaran tauhid yang murni: bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa, bukan manusia, bukan benda, bukan karomah.
Antara Akal dan Iman
Gen Alfarizi hanyalah simbol dari kebangkitan cara berpikir baru di kalangan anak muda Indonesia cara berpikir yang menolak tunduk pada logika mistika. Ia menantang kita semua untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan terhadap hal gaib yang belum tentu ada, tapi juga untuk tidak kehilangan spiritualitas.
Dan mungkin, di sinilah paradoks sekaligus keindahannya:
Anak muda seperti Gen Alfarizi bukan ingin menghancurkan kepercayaan, tapi justru menyelamatkannya dari kebodohan.
Karena di era modern ini, kesaktian sejati bukan lagi bisa berjalan di atas air tapi mampu berjalan di atas logika.