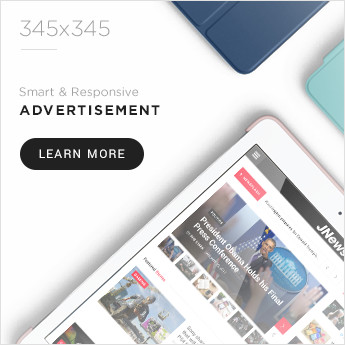Isra’ Mi’raj sering dikenang sebagai peristiwa agung: Nabi Muhammad ﷺ “naik ke langit”, bertemu para nabi, dan menerima perintah shalat. Ia diajarkan di mimbar-mimbar sebagai kisah keajaiban, cahaya, dan kemuliaan. Namun yang kerap luput diceritakan adalah konteks gelap sebelum peristiwa itu terjadi. Isra’ Mi’raj bukan hadiah yang jatuh dari langit secara tiba-tiba, melainkan jawaban ilahi atas penderitaan manusiawi yang nyaris melampaui batas daya tahan seorang Nabi.
Dalam banyak kitab sirah, Isra’ Mi’raj justru datang setelah fase paling menyakitkan dalam hidup Rasulullah ﷺ. Tahun itu dikenal sebagai ‘Āmul Ḥuzn Tahun Kesedihan. Bukan tanpa alasan. Pada fase inilah Nabi kehilangan “sayap pelindung”-nya satu per satu, di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan kekerasan psikologis yang brutal. Tanpa memahami luka ini, Isra’ Mi’raj akan terasa seperti dongeng spiritual, bukan puncak dari perjalanan derita.
Sejarah kenabian menunjukkan satu pola penting: Allah sering memberi cahaya paling terang setelah malam paling gelap. Isra’ Mi’raj adalah contoh paling nyata. Ia bukan pelarian dari penderitaan, tetapi penguatan bagi jiwa yang hampir runtuh. Dan untuk memahaminya, kita harus berani menengok luka-luka yang jarang disorot.
Kehilangan Sayap Pertama: Wafatnya Khadijah
Khadijah binti Khuwailid bukan sekadar istri Nabi. Dalam sirah Ibnu Hisyam dan riwayat Ibnu Sa’d, ia digambarkan sebagai penopang emosional, moral, dan ekonomi dakwah Rasulullah ﷺ. Saat semua orang meragukan kenabian Muhammad, Khadijah adalah yang pertama membenarkan. Saat orang-orang mengejek dan memusuhi, rumah Khadijah menjadi ruang aman terakhir.
Wafatnya Khadijah bukan kehilangan biasa. Nabi kehilangan tempat pulang. Kehilangan suara yang selalu berkata, “Allah tidak akan menghinakanmu.” Dalam riwayat, Rasulullah ﷺ sangat terpukul. Bahkan setelah bertahun-tahun, beliau masih menyebut nama Khadijah dengan mata berkaca-kaca. Aisyah RA meriwayatkan betapa dalam cinta dan ingatan Nabi terhadapnya.
Tanpa Khadijah, dakwah kehilangan pelindung sunyi. Tekanan Quraisy terasa lebih keras karena tidak ada lagi figur terpandang yang berdiri di belakang Nabi. Luka ini tidak kasat mata, tetapi menggerogoti batin. Dan luka inilah yang menjadi pintu pertama menuju Tahun Kesedihan.
Kehilangan Sayap Kedua: Wafatnya Abu Thalib
Jika Khadijah adalah pelindung batin, maka Abu Thalib adalah pelindung sosial. Ia bukan Muslim, tetapi perlindungannya terhadap Nabi bersifat total. Dalam sistem kabilah Arab, posisi Abu Thalib membuat Quraisy berpikir seribu kali sebelum menyentuh Muhammad secara langsung.
Ketika Abu Thalib wafat, tameng itu runtuh. Sirah Nabawiyah mencatat, setelah kematian Abu Thalib, gangguan terhadap Nabi meningkat drastis. Ejekan berubah menjadi kekerasan terbuka. Nabi bukan hanya ditolak sebagai Rasul, tetapi dihinakan sebagai manusia.
Ibn Katsir mencatat bahwa setelah wafatnya Abu Thalib, Nabi pernah dilempari kotoran oleh tetangganya sendiri. Ini bukan sekadar pelecehan fisik, tetapi penghancuran martabat. Seorang Nabi, utusan Tuhan, diperlakukan seperti sampah sosial. Dan semua itu terjadi tanpa pelindung.
Boikot Tiga Tahun: Kelaparan sebagai Senjata
Sebelum wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Nabi dan kaum Muslimin telah melewati boikot ekonomi dan sosial selama hampir tiga tahun. Quraisy mengurung Bani Hasyim dan Bani Muthalib di Syi’b Abu Thalib. Tidak boleh ada jual beli, pernikahan, atau hubungan sosial.
Dalam sirah Ibnu Hisyam disebutkan bahwa anak-anak menangis kelaparan hingga suaranya terdengar keluar lembah. Mereka memakan daun-daunan untuk bertahan hidup. Tangisan itu bukan metafora, tetapi fakta sejarah. Boikot ini adalah bentuk penyiksaan kolektif yang terencana.
Boikot berakhir, tetapi bekasnya tidak hilang. Tubuh lemah, harta habis, dan jiwa terluka. Dalam kondisi inilah Khadijah wafat sebagian ulama sirah menyebutkan, kelelahan dan penderitaan mempercepat kepergiannya. Luka Nabi pun berlapis-lapis.
Diusir dan Dilempari: Tragedi Thaif
Setelah semua pintu di Makkah tertutup, Nabi pergi ke Thaif. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mencari ruang dakwah yang baru. Namun yang ia temui adalah penolakan paling brutal. Penduduk Thaif mengusirnya dan memerintahkan anak-anak serta budak untuk melempari Nabi dengan batu.
Dalam riwayat sahih, kaki Nabi berdarah hingga sandal beliau penuh darah. Malaikat Jibril datang menawarkan untuk membinasakan Thaif, tetapi Nabi menolak. Doanya bukan kutukan, melainkan harapan: “Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui.”
Setelah itu, Nabi duduk sendirian di kebun, menangis dan berdoa. Di titik inilah manusia bernama Muhammad berada pada batas kelelahan total. Dan justru dari titik inilah Isra’ Mi’raj dimulai.
Isra’ Mi’raj: Pelukan Langit bagi Nabi yang Terluka
Para ulama sirah sepakat, Isra’ Mi’raj datang sebagai penghiburan ilahi. Allah tidak langsung mengubah keadaan di bumi, tetapi menguatkan jiwa Rasul-Nya. Shalat diwajibkan bukan sebagai beban, melainkan sebagai sandaran jiwa di tengah penderitaan.
Isra’ Mi’raj mengajarkan satu hal penting: sebelum Allah mengangkat derajat Nabi ke langit, Allah biarkan beliau menyentuh dasar penderitaan manusia. Agar risalah ini tidak lahir dari menara gading, tetapi dari luka yang nyata.
Maka Isra’ Mi’raj bukan sekadar kisah naik ke langit. Ia adalah sejarah tentang seorang Nabi yang hampir patah, lalu dikuatkan. Dan mungkin, di situlah pesan terdalamnya: bahwa iman terbesar sering lahir dari penderitaan yang paling sunyi.