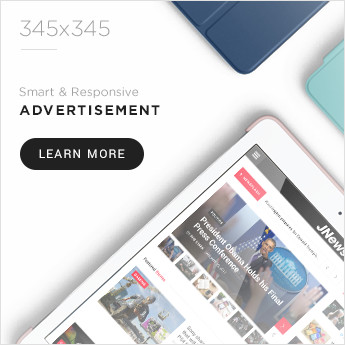Di negeri yang religius, kemiskinan kerap diperlakukan sebagai takdir. Ia dinasihati dengan kesabaran, ditenangkan dengan janji pahala, dan diterima sebagai bagian dari “jalan hidup”. Narasi ini terdengar menenteramkan, tetapi diam-diam berbahaya. Sebab ketika kemiskinan dianggap nasib, maka tanggung jawab sosial dan politik perlahan menghilang.
Padahal, kemiskinan bukan peristiwa alam. Ia tidak turun dari langit tanpa sebab. Kemiskinan adalah hasil dari rangkaian kebijakan, struktur ekonomi, dan pilihan politik yang dibuat—atau gagal dibuat oleh negara. Menyebut kemiskinan sebagai takdir sering kali menjadi cara paling halus untuk membebaskan sistem dari tanggung jawabnya.
Dari Individu ke Struktur: Di Mana Letak Kesalahannya?
Selama ini, diskursus publik sering memusatkan kemiskinan pada individu: kurang kerja keras, rendahnya pendidikan, atau lemahnya etos hidup. Narasi ini tampak masuk akal, tetapi hanya menyentuh permukaan. Ia gagal melihat konteks yang lebih luas: apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk keluar dari kemiskinan?
Akses pendidikan yang timpang, lapangan kerja yang terbatas, upah yang tidak layak, serta kebijakan ekonomi yang lebih ramah modal besar daripada rakyat kecil menciptakan perangkap struktural. Dalam kondisi ini, kerja keras saja tidak cukup. Orang miskin bisa bekerja lebih keras dari siapa pun, tetapi tetap tidak bergerak dari titik yang sama.
Sistem Ekonomi yang Tidak Netral
Sistem ekonomi sering dipresentasikan seolah netral dan teknokratis. Padahal, ia sarat nilai dan kepentingan. Pilihan untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah pilihan politik. Ketika angka makro membaik tetapi ketimpangan melebar, itu bukan kecelakaan, melainkan konsekuensi sistemik.
Ekonom Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan soal angka, melainkan perluasan kemampuan manusia untuk hidup bermartabat. Jika sistem ekonomi gagal menyediakan akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan layak, maka ia sedang memproduksi kemiskinan bukan menguranginya.
Negara Hadir, Tapi Tidak Selalu Membela
Negara sering hadir dalam bentuk regulasi, proyek, dan statistik. Namun kehadiran itu tidak selalu berarti keberpihakan. Banyak kebijakan dibuat atas nama rakyat, tetapi dampaknya justru paling berat dirasakan oleh kelompok miskin. Kenaikan biaya hidup, penggusuran, dan minimnya perlindungan sosial menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berdiri di sisi yang paling membutuhkan.
Dalam situasi seperti ini, kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi krisis keadilan. Negara yang kuat secara administratif, tetapi lemah secara empatik, akan terus mereproduksi kemiskinan.
Agama dan Kritik terhadap Normalisasi Kemiskinan
Dalam perspektif agama, kemiskinan tidak pernah dipandang sebagai kondisi ideal. Islam, misalnya, menjadikan keadilan sosial sebagai inti ajaran. Surah Al-Ma’un dengan tegas mengaitkan iman dengan kepedulian terhadap fakir miskin. Mengabaikan mereka bukan hanya kegagalan sosial, tetapi juga kegagalan moral.
Namun dalam praktiknya, agama kadang justru dipakai untuk menormalisasi kemiskinan. Kesabaran ditekankan tanpa diiringi perjuangan struktural. Padahal, agama sejatinya adalah kritik terhadap sistem yang menindas. Seperti dikatakan Moeslim Abdurrahman, agama seharusnya berpihak, bukan netral di tengah ketimpangan.
Bantuan Sosial: Menolong atau Menenangkan?
Program bantuan sosial sering dipuji sebagai bukti kehadiran negara. Ia memang penting, terutama dalam kondisi darurat. Namun jika bantuan hanya bersifat jangka pendek tanpa pembenahan sistem, maka ia lebih berfungsi sebagai penenang sosial ketimbang solusi.
Bantuan yang tidak disertai reformasi struktural berisiko melanggengkan ketergantungan. Orang miskin dibantu agar bertahan hidup, tetapi tidak diberi jalan untuk keluar dari kemiskinan. Di sinilah kegagalan sistem menjadi semakin nyata.
Demokrasi dan Suara yang Tak Didengar
Secara formal, demokrasi memberi ruang bagi semua suara. Namun dalam praktik, suara orang miskin sering kalah oleh kepentingan elite. Mereka jarang terlibat dalam perumusan kebijakan yang menentukan hidup mereka. Aspirasi mereka disederhanakan menjadi angka dalam survei, bukan pengalaman hidup yang harus dipahami.
Hannah Arendt pernah menekankan bahwa politik sejati adalah ruang bagi manusia untuk tampil dan didengar. Ketika orang miskin tidak memiliki ruang itu, demokrasi kehilangan substansinya. Ia menjadi prosedur tanpa keadilan. Di tengah kegagalan sistem, masyarakat sipil sering mengambil peran. Lembaga pendidikan alternatif, advokasi hukum, dan gerakan sosial tumbuh dari kepedulian warga. Kerja-kerja ini penting dan mulia. Namun mereka tidak boleh dipaksa menggantikan peran negara.
Tanpa perubahan kebijakan, kerja sunyi ini akan terus berhadapan dengan tembok struktural yang sama. Kemiskinan akan tetap ada, hanya wajahnya yang berganti.
Mengakhiri Mitos Takdir
Mengakui bahwa kemiskinan adalah kegagalan sistem bukan berarti meniadakan peran individu. Sebaliknya, ini adalah langkah awal untuk membangun sistem yang adil, di mana kerja keras benar-benar memiliki arti. Tanpa kejujuran ini, kemiskinan akan terus diwariskan, sementara negara sibuk merayakan angka pertumbuhan.
Kemiskinan bukan takdir. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan yang bisa diubah. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu, tetapi apakah kita mau mengubah sistem yang selama ini lebih nyaman bagi segelintir orang. Di titik inilah refleksi sosial menemukan urgensinya. Sebab membiarkan kemiskinan berarti menerima kegagalan sistem sebagai sesuatu yang wajar. Dan itu, pada akhirnya, adalah kegagalan kita bersama sebagai bangsa.