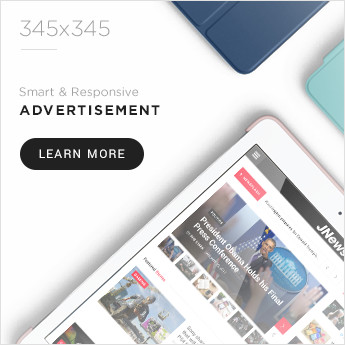Di ruang tamu yang hening, seorang anak duduk menunduk. Matanya sembab, pikirannya lelah. Baru saja ibunya memintanya untuk lebih giat belajar karena nilai matematika turun dua poin. Belum selesai dengan tekanan itu, ayahnya datang menagih keahlian lain: “Sekarang anak-anak harus bisa bahasa Inggris”
Sementara itu, anak ini hanya ingin dimengerti.
Fenomena ini bukan hal baru. Orangtua sibuk menuntut, sementara anak-anak diam-diam sibuk menyesuaikan. Dalam diam mereka berusaha menyenangkan semua orang, tapi kadang melupakan dirinya sendiri.
Tuntutan yang Membebani, Bukan Memotivasi
Di era kompetitif ini, banyak orangtua ingin anaknya “sukses”. Tapi dalam praktiknya, definisi sukses seringkali sempit: nilai tinggi, ranking atas, masuk sekolah favorit, prestasi segudang. Bahkan tidak jarang disertai perbandingan dengan anak tetangga, anak saudara, atau idola di media sosial.
Padahal, menurut riset dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sekitar 74% anak mengalami tekanan psikis karena tuntutan berlebihan dari orangtua, terutama dalam hal akademik. Tekanan ini berkontribusi pada meningkatnya kasus depresi ringan hingga berat pada anak usia sekolah.
Sebuah studi dari UNICEF tahun 2022 di Asia Tenggara juga menunjukkan bahwa lebih dari 30% anak merasa cemas dan takut gagal karena ekspektasi keluarga yang terlalu tinggi.
Pertanyaannya, apakah benar semua tuntutan itu demi kebaikan anak, atau sebenarnya untuk memenuhi ambisi orangtua yang tak tercapai di masa lalu?
Anak Bukan Mesin Prestasi
Anak bukanlah proyek ambisi. Mereka bukan mesin pencetak nilai. Mereka manusia yang sedang tumbuh dan mencari jati diri. Dalam proses ini, mereka butuh didengar, dipahami, dan dituntun bukan ditekan.
Nabi Muhammad SAW memberikan contoh luar biasa dalam mendidik. Beliau tidak menekan, tapi membimbing. Ketika seorang pemuda datang meminta izin untuk berzina, beliau tidak langsung marah. Justru beliau berdialog dengan sabar dan menyentuh hati. Dalam HR. Ahmad, Nabi berkata: “Apakah engkau rela itu terjadi pada ibumu? Pada saudaramu? Pada anak perempuanmu?” Lalu anak muda itu menangis dan berjanji tak akan melakukannya.
Dari sini kita belajar: memahami lebih menyentuh daripada menuntut.
Ketakutan yang Disembunyikan Anak
Banyak anak yang tampak baik-baik saja padahal sedang terluka. Mereka tersenyum di depan orangtua, tapi menangis di kamar. Mereka menyembunyikan luka karena takut mengecewakan. Karena dari kecil, mereka diajarkan bahwa cinta orangtua datang setelah prestasi.
“Kamu hebat karena juara,”
“Papa bangga karena kamu ranking,”
“Kalau kamu gagal, Mama kecewa.”
Kalimat-kalimat semacam ini meski sering diucap dengan niat baik sebenarnya mengajarkan bahwa cinta harus dibayardengan pencapaian. Anak pun tumbuh dengan ketakutan gagal dan takut tidak dicintai.
Dalam jangka panjang, ini berdampak serius. Anak menjadi pribadi yang tidak percaya diri, sulit mengambil keputusan sendiri, bahkan mudah mengalami gangguan kecemasan (anxiety disorder).
Kurikulum yang Tak Mengajarkan Rasa
Masalah ini diperparah dengan sistem pendidikan yang juga terlalu fokus pada kognitif. Nilai akademik diutamakan, sedangkan kecerdasan emosional dan kesadaran diri nyaris diabaikan.
Padahal, menurut psikolog Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence, orang dengan EQ tinggi lebih siap menghadapi kehidupan dibanding mereka yang hanya cerdas secara akademik. Ia menekankan pentingnya empati, kemampuan beradaptasi, dan mengelola emosi hal-hal yang justru jarang diajarkan, baik di sekolah maupun di rumah.
Al-Qur’an tidak pernah memerintahkan orangtua untuk menjadikan anak sebagai alat ambisi. Justru sebaliknya, anak digambarkan sebagai penyejuk mata dan hati.
“Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (qurrota a’yun) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa'”
(QS. Al-Furqan: 74)
Ayat ini tidak bicara soal anak sebagai sumber kebanggaan, tapi sebagai penyejuk hati. Jika anak menjadi sumber luka dan tekanan, maka kita perlu bertanya: Apa yang salah dalam cara kita mencintai mereka?
Menjadi Orangtua yang Mengerti, Bukan Hanya Menuntut
Menjadi orangtua bukan berarti tahu segalanya. Justru, menjadi orangtua adalah proses panjang belajar untuk memahami makhluk kecil yang sedang tumbuh. Tugas kita bukan memaksa anak menjadi seperti kita, tapi mendampingi mereka menjadi diri terbaik mereka.
Tuntutan memang perlu. Tapi seimbangkan dengan dukungan dan pemahaman. Daripada berkata, “Kamu harus jadi juara!”, lebih baik katakan, “Apapun hasilmu, kami selalu mendukungmu berproses.”
Ruang Aman Bernama Rumah
Di dunia yang makin penuh persaingan, rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Tempat di mana mereka boleh gagal, boleh bertanya, dan boleh merasa cukup menjadi dirinya.
Anak yang tumbuh dalam cinta tanpa syarat akan menjadi pribadi yang kuat. Mereka tidak hanya berani sukses, tapi juga berani gagal. Dan itu jauh lebih berharga dari sekadar nilai atau ranking.
Jangan sibuk menuntut, sampai lupa melihat bahwa anak sedang berjuang menyesuaikan. Mungkin bukan mereka yang lambat tumbuh, tapi kita yang terlalu cepat berharap.