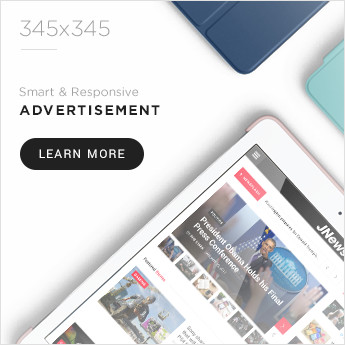Ibadah haji adalah puncak pengabdian spiritual umat Islam yang menuntut kesabaran, pengorbanan, dan ketundukan total. Di Indonesia, antrean haji yang panjang menjadikan setiap kursi sebagai harapan yang ditunggu puluhan tahun. Karena itu, kuota haji bukan sekadar angka administratif, melainkan amanah suci yang menyangkut hak warga negara. Ketika kuota ini dipermainkan, luka yang ditimbulkan bersifat sosial sekaligus spiritual.
Dalam konteks pengelolaan negara, kuota haji adalah mandat publik yang tidak boleh disentuh kepentingan pribadi. Ia dikelola atas nama keadilan, bukan kedekatan, kekuasaan, atau transaksi. Namun realitas menunjukkan bahwa ruang ibadah pun tidak sepenuhnya steril dari logika kekuasaan. Di sinilah masalah bermula.
Al-Qur’an mengingatkan, “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil” (QS. Al-Baqarah: 188). Ayat ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang cara kotor yang merusak tatanan. Dalam urusan haji, kebatilan itu berlipat karena menyentuh kesucian ibadah.
Kuota Haji sebagai Amanah Publik
Kuota haji berasal dari kesepakatan internasional yang dipercayakan kepada negara untuk dibagikan secara adil. Ia bukan milik pejabat, bukan pula hak lembaga tertentu. Setiap penyimpangan dari prinsip keadilan adalah pengkhianatan terhadap warga yang telah menunggu lama. Di titik ini, keadilan sosial dipertaruhkan.
Masalah muncul ketika kuota diperlakukan sebagai ruang diskresi tanpa transparansi. Jalur khusus, percepatan ilegal, dan titipan kepentingan membuka celah ketidakadilan. Bahasa administratif sering dipakai untuk menutupi praktik yang sesungguhnya melanggar etika. Publik hanya melihat hasil, bukan proses.
Islam memandang amanah sebagai kewajiban berat. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa: 58). Menggeser hak jamaah demi kepentingan tertentu adalah pelanggaran yang jelas. Dalam haji, pengkhianatan ini menyentuh wilayah iman.
Korupsi Struktural dalam Pengelolaan Haji
Korupsi kuota haji tidak selalu hadir dalam bentuk uang tunai. Ia sering muncul sebagai barter kepentingan, balas jasa politik, atau keuntungan tidak langsung. Penyalahgunaan kewenangan menjadi inti persoalan. Dampaknya luas, meski jejaknya kerap samar.
Secara hukum, penyalahgunaan jabatan adalah tindak pidana. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik adalah korupsi. Kerugian tidak selalu harus berupa uang negara yang hilang. Hilangnya hak warga adalah kerugian nyata.
Korupsi struktural sering berlindung di balik kata “kebijakan”. Padahal kebijakan tanpa keadilan hanyalah legitimasi formal bagi kezaliman. Negara hukum tidak memberi ruang aman bagi praktik semacam ini. Terlebih ketika menyangkut ibadah.
Kesalehan Simbolik sebagai Tameng
Ironi terbesar dalam pengelolaan haji adalah penggunaan simbol agama untuk meredam kritik. Bahasa ibadah, niat baik, dan dalih maslahat sering dipakai sebagai tameng. Kesalehan simbolik dijadikan pelindung praktik yang tidak adil. Di sinilah agama direduksi menjadi alat pembenaran.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami” (HR. Muslim). Penipuan dalam urusan ibadah bukan kesalahan kecil. Ia merusak kepercayaan umat terhadap institusi dan nilai agama itu sendiri. Kesalehan sejati tidak pernah bertentangan dengan keadilan.
Ketika agama dipakai untuk menutup penyimpangan, yang rusak bukan hanya sistem. Yang runtuh adalah kepercayaan kolektif. Ibadah kehilangan kesuciannya ketika dikelola dengan logika untung-rugi. Di titik ini, kritik menjadi kewajiban moral.
Ketika Allah Membuka yang Disembunyikan
Sejarah selalu menunjukkan bahwa kebatilan jarang tersembunyi selamanya. Penyimpangan yang dianggap aman perlahan terkuak melalui audit, laporan, dan kesaksian. Yang kecil terakumulasi menjadi bukti. Tirai runtuh karena rapuh dari dalam.
Al-Qur’an menyatakan, “Dan katakanlah: Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap” (QS. Al-Isra: 81). Kebatilan mungkin tampak kuat, tetapi tidak berakar. Ia runtuh oleh dustanya sendiri. Keadilan Ilahi bekerja melalui sebab-sebab duniawi.
Pembukaan keadilan bukan sekadar hukuman. Ia adalah peringatan bahwa amanah ibadah tidak bisa dipermainkan. Tidak ada kekuasaan yang cukup kuat untuk menipu keadilan Tuhan. Langit tidak pernah lalai mencatat.
Negara Hukum dan Tanggung Jawab Moral
Negara memiliki kewajiban menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Transparansi pengelolaan haji bukan pilihan, melainkan keharusan. Mekanisme pengawasan harus dibuka agar publik bisa menilai keadilan distribusi kuota. Tanpa itu, kepercayaan akan terus runtuh.
Hukum dan agama tidak pernah bertentangan dalam soal keadilan. Negara menindak melalui pasal, agama menilai melalui nurani. Keduanya bertemu pada satu titik: amanah. Ketika amanah dilanggar, sanksi adalah keniscayaan.
Di sinilah peran publik menjadi penting. Kritik bukan permusuhan terhadap agama. Ia justru upaya menyelamatkan kesucian ibadah dari penyimpangan kekuasaan. Diam hanya memperpanjang ketidakadilan.
Mengembalikan Kesucian Ibadah
Korupsi kuota haji adalah pengkhianatan ganda terhadap manusia dan Tuhan. Ia merampas hak jamaah dan merusak makna ibadah. Dalam urusan seperti ini, netralitas moral tidak relevan. Kezaliman harus disebut sebagai kezaliman.
Haji bukan sekadar perjalanan fisik ke Tanah Suci. Ia adalah ujian amanah bagi mereka yang mengelolanya. Ketika amanah itu dikhianati, keadilan akan mencari jalannya sendiri.
Dan ketika tirai akhirnya dibuka, yang runtuh bukan hanya pelaku. Yang runtuh adalah ilusi bahwa kekuasaan bisa memperjualbelikan ibadah tanpa konsekuensi.