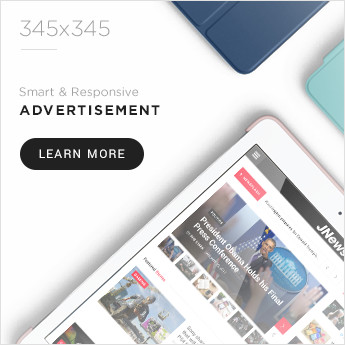Dalam sejarah panjang agama-agama, selalu ada godaan yang berulang: mendekat ke pusat kekuasaan. Istana menawarkan perlindungan, mimbar menawarkan pengaruh, dan kekuasaan menjanjikan stabilitas. Namun di titik itulah agama diuji. Ketika agama terlalu akrab dengan kekuasaan, sering kali yang justru menjauh adalah mereka yang paling membutuhkan pembelaan: orang-orang kecil, kaum miskin, dan mereka yang hidup di pinggiran sejarah.
Di banyak ruang publik hari ini, agama tampak hadir dalam seremoni kenegaraan, doa-doa resmi, dan simbol-simbol moral. Namun pertanyaannya menggelitik: apakah agama masih cukup lantang membela yang lemah, atau justru lebih sibuk menjaga kedekatannya dengan yang berkuasa?
Sejarah Agama: Lahir dari Jeritan Kaum Tertindas
Jika menengok ke belakang, hampir semua agama besar lahir dari pengalaman penderitaan. Para nabi datang bukan dari istana, melainkan dari lorong-lorong kehidupan yang keras. Musa berhadapan dengan Firaun, Isa berdiri bersama kaum miskin, dan Muhammad membawa pesan tauhid yang mengguncang struktur sosial Mekah yang timpang.
Agama sejak awal adalah kritik terhadap ketidakadilan. Ia hadir untuk membebaskan, bukan menenangkan. Karena itu, keberpihakan pada yang lemah bukanlah pilihan ideologis, melainkan identitas moral agama itu sendiri. Ketika agama kehilangan keberpihakan ini, ia berisiko kehilangan ruhnya.
Kekuasaan dan Daya Rusak Kesalehan
Kekuasaan memiliki daya tarik yang halus namun kuat. Ia mampu mengubah bahasa agama menjadi lebih lunak, lebih kompromistis. Kritik sosial diganti dengan doa keselamatan, keberpihakan diganti dengan netralitas semu. Dalam proses ini, kesalehan berubah dari energi pembebasan menjadi alat legitimasi.
Filsuf Jürgen Habermas pernah mengingatkan tentang bahaya ketika agama berhenti menjadi sumber kritik moral dalam ruang publik. Agama yang hanya mengafirmasi kekuasaan akan kehilangan fungsi profetiknya. Ia tidak lagi menjadi suara nurani, melainkan gema dari kepentingan yang dominan.
Yang Lemah dan Yang Tak Terlihat
Keberpihakan pada yang lemah bukan sekadar soal memberi sedekah. Ia menuntut pengakuan terhadap mereka yang sering tak terlihat: buruh upah rendah, petani yang kehilangan lahan, masyarakat adat yang terdesak, serta warga miskin kota yang hidup di bawah bayang-bayang penggusuran.
Dalam banyak kasus, mereka bukan hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin secara politik. Suara mereka jarang masuk dalam pengambilan keputusan. Agama, jika setia pada misi awalnya, seharusnya menjadi corong bagi suara-suara yang terbungkam ini.
Al-Ma’un dan Teologi Keberpihakan
Dalam tradisi Islam, Surah Al-Ma’un adalah teks kunci yang menegaskan teologi keberpihakan. Iman diukur bukan dari ritual, melainkan dari sikap terhadap anak yatim dan fakir miskin. Mengabaikan mereka sama dengan mendustakan agama.
Pesan ini dibaca secara radikal oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang menjadikan Al-Ma’un sebagai landasan gerakan sosial. Agama tidak berhenti di masjid, tetapi bergerak ke sekolah, rumah sakit, dan kerja-kerja pemberdayaan. Di sini, agama menemukan wujudnya yang paling konkret: membela kehidupan.
Agama yang Netral adalah Agama yang Memihak Diam-Diam
Sering kali, agama berlindung di balik klaim netralitas. Tidak berpihak, katanya, demi menjaga persatuan. Namun dalam situasi timpang, netralitas justru berarti membiarkan ketidakadilan berlangsung. Seperti dikatakan Desmond Tutu, jika Anda netral dalam situasi ketidakadilan, Anda telah memilih pihak penindas.
Agama tidak bisa bersikap netral di tengah ketimpangan. Diamnya agama justru menjadi keberpihakan diam-diam pada status quo. Karena itu, keberanian moral menjadi syarat utama kesalehan sosial.
Ruang Publik dan Tanggung Jawab Moral Agama
Di era demokrasi, agama sering diperingatkan agar tidak “terlalu jauh” masuk ke politik. Peringatan ini penting agar agama tidak dijadikan alat kekuasaan. Namun ada perbedaan besar antara politisasi agama dan etika agama dalam politik.
Agama tidak perlu merebut kekuasaan, tetapi ia wajib mengoreksi kekuasaan. Ia harus hadir sebagai kompas moral, bukan pemain politik. Dengan cara ini, agama menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan, sekaligus tetap dekat dengan penderitaan manusia. Keberpihakan agama pada yang lemah bukan berarti membenci yang berkuasa. Ia berarti mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Agama berfungsi mengingatkan bahwa legitimasi sejati kekuasaan terletak pada kemampuannya melindungi yang paling rentan.
Dalam konteks Indonesia hari ini, tantangannya bukan kekurangan simbol religius, melainkan keberanian moral. Agama dituntut untuk kembali menjadi suara profetik yang jujur, bahkan ketika suaranya tidak nyaman bagi penguasa.
Agama sebagai Penjaga Nurani Publik
Pada akhirnya, agama akan selalu dihadapkan pada pilihan: berpihak pada yang lemah atau bersekutu dengan yang kuat. Pilihan ini menentukan apakah agama tetap menjadi sumber harapan atau berubah menjadi ornamen kekuasaan.
Mengapa agama harus berpihak pada yang lemah? Karena di situlah ia lahir, di situlah ia diuji, dan di situlah ia menemukan maknanya yang paling dalam. Tanpa keberpihakan itu, agama mungkin tetap ramai dirayakan, tetapi kehilangan jiwa pembebasannya. Dan agama yang kehilangan keberpihakan pada yang lemah, pada akhirnya, hanyalah bayangan dari dirinya sendiri.