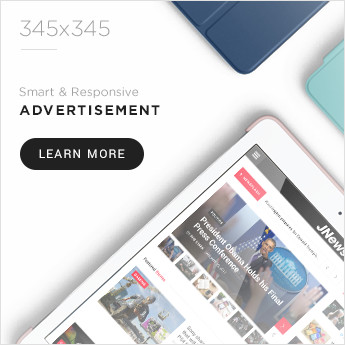Menjelang akhir tahun, raport dibagikan. Angka-angka tertulis rapi, sebagian besar hijau, bahkan nyaris sempurna. Orang tua tersenyum, sekolah merasa aman, dan sistem terlihat berjalan baik-baik saja. Namun di balik lembaran nilai itu, ada pertanyaan yang semakin sulit dihindari: apakah pendidikan kita benar-benar semakin bermutu, atau sekadar semakin pandai menaikkan angka?
Pertanyaan ini tidak lahir dari sikap sinis, melainkan dari kenyataan sehari-hari di ruang kelas. Banyak guru mengakui dengan nada lirih bahwa hari ini nilai bisa diatur, disesuaikan, bahkan “diselamatkan”. Bukan karena guru ingin berbohong, tetapi karena sistem menekan ke satu arah: jangan sampai ada nilai jelek yang mengganggu citra sekolah dan laporan pusat. Di sinilah ironi pendidikan kita bermula.
Angka sebagai Tujuan, Bukan Alat
Sejatinya, nilai adalah alat evaluasi, bukan tujuan akhir. Ia seharusnya membantu guru memahami kemampuan siswa, dan membantu siswa mengenali kekuatan serta kekurangannya. Namun dalam praktiknya, nilai berubah fungsi menjadi penentu kelulusan, reputasi sekolah, bahkan indikator keberhasilan kebijakan pendidikan.
Ketika angka menjadi segalanya, maka proses belajar perlahan kehilangan makna. Siswa belajar demi nilai, bukan demi pemahaman. Guru mengajar demi laporan administrasi, bukan demi pertumbuhan intelektual. Sekolah berlomba menampilkan statistik kelulusan, bukan kualitas lulusan.
Tak mengherankan jika kita menjumpai siswa dengan nilai tinggi tetapi gagap membaca teks panjang, kesulitan menulis argumen sederhana, atau tidak mampu berpikir kritis. Nilai naik, tetapi daya nalar justru turun.
Guru di Persimpangan Etika dan Sistem
Di balik fenomena ini, guru berada pada posisi yang paling dilematis. Di satu sisi, guru adalah pendidik yang dituntut menjunjung kejujuran akademik. Di sisi lain, guru adalah bagian dari sistem birokrasi pendidikan yang sarat tekanan.
Tekanan datang dari berbagai arah: orang tua yang tidak terima anaknya bernilai rendah, sekolah yang takut dicap gagal, hingga sistem pelaporan nasional yang tidak memberi ruang pada nilai apa adanya. Dalam kondisi seperti ini, banyak guru akhirnya memilih “jalan aman”: menaikkan nilai, memberi remedial berulang, atau menyamakan skor demi memenuhi standar KKM.
Ini bukan soal moral individu guru semata, melainkan masalah struktural. Ketika kejujuran justru berisiko, maka manipulasi menjadi normal. Ketika integritas tidak dilindungi sistem, maka kompromi dianggap wajar.
Kurikulum Merdeka: Harapan yang Tersandung Realitas
Kurikulum Merdeka datang dengan semangat pembebasan: pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif, dan fokus pada kompetensi. Secara konsep, kurikulum ini adalah angin segar. Namun di lapangan, implementasinya sering tersandung realitas.
Tidak semua guru mendapatkan pelatihan yang memadai. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya pendukung. Bahkan tidak semua pemangku kebijakan memahami filosofi di balik kurikulum tersebut. Akibatnya, Kurikulum Merdeka sering hanya berganti nama, sementara praktik lama tetap dipertahankan.
Penilaian seharusnya lebih kualitatif dan reflektif. Namun yang terjadi justru sebaliknya: format boleh baru, tetapi mentalitas lama masih berkuasa. Nilai tetap dikejar, mutu tetap terpinggirkan. Salah satu penyakit kronis pendidikan kita adalah beban administrasi. Guru lebih banyak mengisi format daripada mengembangkan metode. Lebih sibuk menyusun laporan daripada mendampingi siswa yang tertinggal.
Dalam situasi seperti ini, wajar jika pembelajaran kehilangan ruhnya. Kelas menjadi rutinitas, bukan ruang eksplorasi. Proyek menjadi formalitas, bukan pengalaman bermakna. Pendidikan berubah menjadi proses teknis, bukan proses humanis. Padahal, mutu pendidikan tidak lahir dari dokumen yang rapi, melainkan dari relasi hidup antara guru dan murid. Dari dialog, dari kesalahan yang diperbaiki, dari proses panjang yang jujur.
Siswa yang Lulus, Tapi Tidak Siap Hidup
Dampak jangka panjang dari ilusi nilai ini sangat serius. Kita melahirkan generasi yang lulus secara administratif, tetapi rapuh secara kompetensi. Mereka membawa ijazah, namun tidak membawa kepercayaan diri berpikir. Mereka hafal jawaban, tetapi tidak terbiasa bertanya.
Ketika dunia kerja menuntut kreativitas dan ketangguhan, banyak lulusan kebingungan. Ketika masyarakat membutuhkan empati dan etika, pendidikan kita terlalu sibuk mengurus ranking. Ini bukan semata kegagalan siswa, melainkan kegagalan sistem yang lebih mencintai angka daripada manusia.
Akhir Tahun: Saatnya Jujur pada Pendidikan
Akhir tahun seharusnya menjadi waktu refleksi, bukan sekadar rekapitulasi. Dunia pendidikan perlu keberanian untuk jujur: bahwa tidak semua yang bernilai tinggi itu bermutu, dan tidak semua yang bermutu itu bisa diwakili angka.
Kita perlu sistem yang melindungi kejujuran guru, mendidik orang tua agar memahami proses belajar, dan memberi ruang pada siswa untuk tumbuh sesuai kemampuannya. Pendidikan tidak boleh terus berjalan dalam kepura-puraan kolektif.
Jika pendidikan adalah investasi masa depan, maka kebohongan hari ini adalah krisis esok hari.
Mungkin sudah saatnya kita berdamai dengan kenyataan bahwa nilai rendah bukan aib, tetapi tanda bahwa ada proses yang harus diperbaiki. Yang berbahaya bukanlah siswa yang belum mampu, melainkan sistem yang menolak mengakui ketidakmampuannya sendiri.
Nilai boleh naik, tetapi mutu harus lebih dulu dijaga. Jika tidak, pendidikan kita hanya akan melahirkan generasi yang terlihat pintar di atas kertas, namun kehilangan daya hidup di dunia nyata. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini kembali menghantui akhir tahun kita: apakah kita sedang mendidik anak-anak, atau sekadar merapikan laporan?