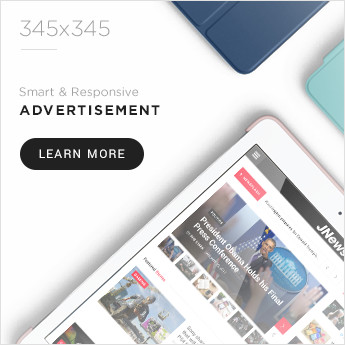Sekolah hari ini semakin sibuk mencetak anak-anak yang pintar, tetapi sering lupa memastikan mereka juga menjadi manusia. Nilai akademik naik, prestasi dicatat, sertifikat dikoleksi. Namun pada saat yang sama, kepekaan sosial justru menurun, empati menipis, dan nurani kerap tertinggal di luar ruang kelas. Inilah paradoks pendidikan kita hari ini: cerdas secara kognitif, rapuh secara etis.
Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seiring pendidikan yang semakin teknokratis terjebak pada angka, target, dan capaian administratif. Pendidikan direduksi menjadi soal hasil, bukan proses. Padahal, esensi pendidikan sejatinya adalah pembentukan manusia seutuhnya: akal, hati, dan tindakan.
Pintar yang Tak Pernah Diajak Merasa
Kita sering bangga ketika siswa mampu menjawab soal rumit, menghafal teori panjang, atau lulus dengan nilai tinggi. Tetapi kita jarang bertanya: apakah mereka mampu merasa? Apakah mereka peka terhadap penderitaan orang lain? Apakah mereka memiliki rasa tanggung jawab sosial?
Tidak sedikit anak didik yang mampu berbicara tentang moral di atas kertas, tetapi gagap ketika dihadapkan pada kenyataan hidup: melihat ketidakadilan, kemiskinan, bencana, atau ketimpangan sosial. Mereka tahu definisi empati, tetapi tidak tergerak untuk menolong. Mereka hafal norma, tetapi terbiasa melanggarnya saat tak diawasi. Di sinilah letak masalah pendidikan tanpa etika: ia melahirkan manusia yang pandai menjelaskan kebaikan, tetapi asing dalam mempraktikkannya.
Etika yang Terpinggirkan oleh Kurikulum
Dalam banyak kurikulum, etika sering ditempatkan sebagai pelengkap, bukan inti. Ia hadir sebagai mata pelajaran tertentu, bukan sebagai ruh yang menjiwai seluruh proses belajar. Akibatnya, etika dipahami sebagai teori, bukan laku hidup.
Padahal, etika tidak cukup diajarkan; ia harus diteladankan, dihidupkan, dan dialami. Tidak ada gunanya berbicara tentang kejujuran jika sistem pendidikan sendiri menormalisasi kecurangan: manipulasi nilai, toleransi terhadap plagiarisme, atau budaya “asal lulus”.
Ketika sekolah mengajarkan bahwa nilai lebih penting daripada kejujuran, maka jangan heran jika kelak lahir generasi yang menghalalkan segala cara demi sukses. Pendidikan semacam ini bukan hanya gagal membentuk karakter, tetapi berpotensi merusak masa depan bangsa.
Guru di Tengah Sistem yang Kering Nilai
Guru sejatinya adalah pendidik nilai. Namun hari ini, banyak guru terjebak dalam sistem yang menuntut mereka lebih menjadi administrator ketimbang pendidik. Waktu habis untuk mengisi laporan, menyusun perangkat, mengejar target kurikulum, dan menyesuaikan standar penilaian.
Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk membangun dialog etis semakin sempit. Padahal, nilai-nilai seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kepedulian sosial justru tumbuh dari interaksi hidup antara guru dan murid—bukan dari modul atau rubrik penilaian.
Guru yang ingin menanamkan nilai sering kali harus berhadapan dengan realitas pahit: ketika menegakkan kejujuran dianggap menyulitkan, dan ketika bersikap tegas justru diprotes oleh sistem dan orang tua. Maka, pendidikan etika pun sering kalah oleh pragmatisme.
Ketika Sekolah Terlepas dari Realitas Sosial
Pendidikan tanpa etika juga terlihat dari keterputusan sekolah dengan realitas sosial di sekitarnya. Banyak siswa belajar di ruang kelas yang steril dari masalah nyata: kemiskinan, ketidakadilan, bencana, konflik, dan penderitaan sosial lainnya.
Akibatnya, ilmu menjadi kering, kehilangan konteks kemanusiaan. Siswa bisa pandai berhitung, tetapi tidak peka terhadap ketimpangan. Bisa lancar berbicara, tetapi tidak mampu mendengar jeritan sesama. Bisa menguasai teknologi, tetapi kehilangan kepekaan moral dalam menggunakannya.
Pendidikan semacam ini melahirkan generasi yang efisien, tetapi tidak berbelas kasih.
Islam, Etika, dan Pendidikan Manusia Seutuhnya
Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses tazkiyatun nafs penyucian dan pembentukan jiwa. Ilmu tanpa akhlak dipandang sebagai bahaya, bukan kemajuan. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa misi utama beliau adalah menyempurnakan akhlak manusia.
Artinya, pendidikan yang mengabaikan etika bukan hanya cacat secara pedagogis, tetapi juga problematis secara teologis. Ilmu yang tidak melahirkan keadaban akan menjauhkan manusia dari tujuan kemanusiaannya sendiri.
Dalam tradisi pemikiran Islam dan filsafat humanistik, pendidikan selalu diarahkan untuk membentuk manusia yang cerdas akal, lembut hati, dan bertanggung jawab sosial. Ketika salah satu unsur ini hilang, maka pendidikan kehilangan maknanya.
Pintar Tanpa Etika: Ancaman Masa Depan
Sejarah menunjukkan bahwa banyak kerusakan besar justru dilakukan oleh orang-orang pintar yang kehilangan etika. Korupsi, manipulasi kekuasaan, eksploitasi alam, dan kejahatan struktural sering dikerjakan oleh mereka yang berpendidikan tinggi, tetapi miskin nurani.
Inilah bahaya terbesar pendidikan tanpa etika: ia melahirkan manusia yang memiliki kemampuan besar, tetapi tanpa kompas moral. Jika kekuasaan jatuh ke tangan orang-orang seperti ini, maka ilmu berubah menjadi alat penindasan, bukan pembebasan.
Mengembalikan Etika ke Jantung Pendidikan
Akhirnya, pendidikan perlu kembali pada pertanyaan mendasar: untuk apa kita mendidik? Jika jawabannya hanya demi kompetisi dan angka, maka kita sedang membangun generasi yang kosong secara batin. Tetapi jika pendidikan dimaknai sebagai upaya memanusiakan manusia, maka etika harus ditempatkan di jantungnya.
Sekolah harus menjadi ruang aman untuk belajar jujur, berempati, dan bertanggung jawab. Guru harus diberi ruang dan perlindungan untuk menegakkan nilai. Kurikulum harus berani menempatkan kemanusiaan di atas statistik.
Karena bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar, tetapi manusia-manusia yang peka, beradab, dan berani berdiri di pihak yang benar. Dan mungkin, ukuran keberhasilan pendidikan yang paling jujur bukanlah seberapa tinggi nilai siswa, melainkan seberapa dalam nurani mereka tumbuh.