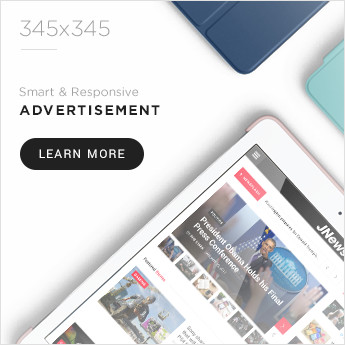Di atas kertas, sekolah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi setiap anak. Tempat menumbuhkan keberanian, bukan ketakutan. Namun realitas di Indonesia hari ini berkata lain: sekolah justru sering menjadi sumber trauma yang menghancurkan masa depan. Kasus demi kasus bullying muncul seperti gelombang tanpa jeda. Terbaru, seorang siswa SMP di Bandar Lampung terpaksa putus sekolah setelah terus-menerus menjadi korban perundungan. Bukan karena nilai yang buruk, melainkan karena ia tak kuat lagi menghadapi ejekan, cemoohan, dan kekerasan psikis yang diterimanya setiap hari di ruang kelas.
Pertanyaannya kemudian: ke mana semua program anti-bullying yang digembar-gemborkan pemerintah dan sekolah selama ini?
Sekolah Tempat Belajar, atau Taman Kekerasan Terselubung?
Kasus di Bandar Lampung ini hanyalah satu dari potret besar gunung es. Tidak sedikit anak Indonesia yang bangun pagi dengan rasa cemas, bukan semangat belajar. Korban bullying seringkali diperlakukan sebagai masalah, bukan pihak yang perlu dilindungi.
Yang lebih menyakitkan, ketika kasus mencuat ke publik, sekolah cenderung defensif. Mereka takut “nama baik institusi rusak”. Maka korban diminta diam. Keluarga ditekan untuk tidak memperpanjang masalah. Pelaku menerima teguran ringan yang tak membuat mereka jera.
Fenomena ini menunjukkan satu hal: reputasi sekolah jauh lebih penting daripada keselamatan muridnya.
Padahal dunia pendidikan seharusnya memiliki satu prinsip utama: tidak ada pembelajaran yang berhasil dalam lingkungan yang tidak aman. Jika sekolah gagal menyediakan rasa aman, maka sekolah telah gagal dalam fungsi terdasarnya.
Program Anti-Bullying: Ada di Spanduk, Mati di Lapangan
Setiap tahun, Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah meluncurkan berbagai program anti-bullying. Ada Satgas Perlindungan Anak, deklarasi sekolah ramah anak, modul perilaku positif, hingga seminar tentang karakter.
Namun mari bertanya jujur: berapa banyak sekolah yang benar-benar melaksanakan itu?
Spanduk anti-bullying terpampang besar di depan sekolah, sementara di dalam kelas, seorang anak menangis karena diejek wajahnya. Poster “Stop Perundungan” tertempel di dinding koridor, tapi di toilet belakang ada siswa yang dipukuli teman-temannya hanya karena berbeda fisik atau latar ekonomi.
Program berjalan hanya saat ada kunjungan pejabat.
Setelah kamera dimatikan, semuanya kembali seperti semula.
Inilah ironi pendidikan kita: lebih sibuk pencitraan ketimbang perlindungan.
Korban yang Disalahkan, Pelaku yang Dimaklumi
Melihat banyak kasus, orang dewasa justru sering menyalahkan korban:
“Kamu harus lebih kuat.”
“Namanya juga anak-anak, wajar bercanda begitu.”
“Jangan terlalu baper.”
Narasi ini menormalisasi kekerasan, mematikan empati, dan memaksa korban merasa salah atas luka yang mereka alami. Sementara pelaku tumbuh tanpa kesadaran bahwa perilaku mereka merusak hidup orang lain.
Seharusnya yang ditanyakan adalah:
kenapa ada anak yang merasa berhak merendahkan anak lain?
darimana mereka belajar bahwa kekuasaan dapat ditunjukkan lewat intimidasi?
Ketika bullying menjadi budaya, itu bukan hanya kegagalan individu melainkan kegagalan sistem pendidikan.
Dampaknya Nyata: Putus Sekolah, Depresi, Hingga Bunuh Diri
Bullying bukan sekadar lelucon kasar. Ia meninggalkan luka dalam yang tak terlihat:
- rasa tidak berharga
- kecemasan sosial
- depresi berkepanjangan
- hilangnya motivasi belajar
Pada kasus di Bandar Lampung, tekanan psikologis membuat seorang anak takut ke sekolah. Ia memilih berhenti, bukan karena malas, melainkan karena ingin selamat dari rasa sakit yang tak dihentikan siapa pun.
Jika anak harus meninggalkan sekolah hanya untuk merasa aman, ada yang sangat keliru dalam sistem ini.
Sekolah Seharusnya Jadi Benteng Terakhir, Bukan Penonton
Ketika bullying terjadi, seringkali guru berkata:
“Kami tidak tahu apa yang terjadi.”
“Itu terjadi di luar pantauan kami.”
“Kami sudah menasihati mereka untuk rukun.”
Nasihat tanpa tindakan hanyalah formalitas kosong.
Sekolah harus berubah dari penonton pasif menjadi penjaga aktif yang siap membela hak anak. Guru bukan sekadar pengajar, tetapi pelindung karakter dan martabat setiap peserta didik. Kepala sekolah harus punya keberanian menindak tegas pelaku meskipun anak pejabat, meskipun anak donatur sekolah.
Karena hak untuk aman tidak boleh dinegosiasikan.
Saatnya Mengakui Kita Gagal Lindungi Anak-Anak
Kita boleh marah pada pelaku bullying, tetapi kemarahan kita seharusnya juga diarahkan pada sistem yang membiarkannya terjadi. Pada institusi yang mengutamakan ranking di atas kesehatan mental. Pada masyarakat yang masih bercanda tentang fisik, warna kulit, pekerjaan orang tua, dan perbedaan.
Jika ada anak yang memilih putus sekolah karena bullying, kita semua turut bersalah.
Apa yang Harus Dilakukan?
Perubahan sistemik harus dimulai dari:
- mekanisme pelaporan yang melindungi korban
- pendampingan psikolog profesional di sekolah
- pendidikan karakter yang tidak hanya formalitas
- sanksi tegas bagi pelaku dan pembiaran oleh guru
- pelibatan orang tua secara serius
Anti-bullying bukan kampanye musiman.
Ini perjuangan menjaga masa depan bangsa.
Akhirnya…
Tahun demi tahun, cita-cita pendidikan Indonesia terus digaungkan: mencetak generasi cerdas, beriman, berakhlak mulia. Namun bagaimana jadinya jika generasi itu tumbuh dalam ketakutan?
Anak yang terluka hari ini adalah masa depan bangsa yang hancur besok. Bandar Lampung hanya satu cerita. Di kota dan desa lain, masih banyak suara anak yang terdiam karena takut. Kini kita harus bertanya kepada negara, kepada sekolah, kepada diri kita sendiri:
Mau sampai kapan anak-anak harus menderita sebelum kita benar-benar peduli?
Jika sekolah bukan tempat aman, maka ke mana lagi mereka harus pergi?