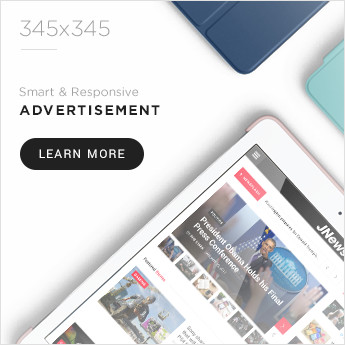Gelombang polemik yang melibatkan sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama beberapa waktu terakhir menimbulkan perbincangan keras di ruang publik. Dari isu “tauhid rokok” yang sempat membuat warganet geleng kepala, hingga klarifikasi kontroversial yang menyeret nama Gus Elham, percakapan tentang “gus-gusan” kini menjadi sorotan nasional. Di tengah keriuhan itu, muncullah suara yang berbeda lebih tenang, lebih jernih, dan jauh lebih menyejukkan. Suara itu datang dari H.M. Abdurrahman Al Kautsar, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Kautsar.
Ketika banyak orang terlibat saling sindir dan membela diri, Gus Kautsar justru mengajak semua pihak, terutama santri NU, untuk muhasabah. Baginya, kritik bukanlah musuh; kritik adalah cermin yang seharusnya digunakan untuk bercermin, bukan untuk dipatahkan. Dan di saat sebagian tokoh publik terjebak pada respons defensif, beliau hadir dengan akhlak yang lembut namun tegas, mengingatkan bahwa kemuliaan santri tidak dibangun dari retorika, tapi dari keteladanan.
Polemik “Gus-Gusan”: Ketika Gelar Tak Lagi Sejalan dengan Akhlak
Beberapa tahun terakhir, istilah “gus-gusan” muncul sebagai kritik sosial terhadap fenomena sebagian tokoh muda yang membawa identitas keagamaan, tetapi perilakunya kerap menimbulkan kontroversi. Ketika gelar “Gus” yang seharusnya menjadi simbol keilmuan, akhlak luhur, dan keteladanan dipakai sembarangan, publik pun merespons dengan kekecewaan.
Kasus “tauhid rokok” yang meledak di media sosial, misalnya, membuat publik mempertanyakan kewarasan argumen keagamaan yang ditampilkan. Begitu pula klarifikasi demi klarifikasi yang justru memunculkan keraguan baru, seolah kedewasaan moral sedang diuji, tetapi tak kunjung lulus dari ujian itu.
Dalam keriuhan itu, sebagian publik bahkan mulai mempertanyakan kualitas pendidikan pesantren, sebuah kekhawatiran yang tentu menyakitkan bagi lembaga yang telah terbukti berperan besar membangun karakter bangsa. Namun di titik inilah, Gus Kautsar hadir dan berkata santri tidak boleh hanya marah, tetapi harus bertanya pada diri sendiri: mengapa masyarakat bisa mencemooh?
Gus Kautsar: Kritik Bukan untuk Dilawan, Tetapi untuk Diresapi
Di saat banyak pihak mencari kambing hitam, Gus Kautsar justru membuka pintu muhasabah selebar-lebarnya. Beliau menegaskan bahwa kritik terhadap sebagian tokoh muda tidak boleh dianggap sebagai serangan terhadap NU atau pesantren. Kritik itu, katanya, adalah momentum untuk berbenah.
Yang lebih menggetarkan adalah kalimatnya yang sederhana namun menghunjam:
“Santri dicemooh karena tidak mampu menunjukkan kepada masyarakat betapa cinta dan ikhlasnya guru-guru NU mengajar kalian dengan tulus.”
Pernyataan ini bukan menyalahkan santri, tetapi mengajak mereka untuk kembali kepada jati diri. Sebab para kiai NU tidak pernah mengajarkan kesombongan, tidak pernah mendidik murid-muridnya untuk merasa paling benar, apalagi menjadikan agama sebagai gimmick viral. Para kiai mengajarkan kesabaran, kelapangan dada, dan keikhlasan nilai yang justru hilang dalam sebagian konten dakwah hari ini.
Di sinilah letak kebijaksanaan Gus Kautsar: ia tidak menutup mata terhadap kesalahan, tetapi juga tidak membiarkan kesalahan menjadi bahan permusuhan. Ia menjadikan kritik sebagai wasilah perbaikan, bukan bahan untuk membentengi ego.
Kembali kepada Keteladanan: Santri Harus Menjadi Wajah Akhlak Guru-Gurunya
Menurut Gus Kautsar, masalah utama bukan pada masyarakat yang mengkritik, tetapi pada santri yang gagal menunjukkan apa yang sebenarnya diajarkan para guru NU: akhlak yang santun, ilmu yang mendalam, dan keikhlasan yang tak bersyarat.
Santri hari ini hidup dalam era media sosial, di mana semua hal bisa menjadi konten. Tetapi ketika konten melampaui batas kesopanan, atau ketika gelar “Gus” dipakai sebagai tameng kesalahan, masyarakat pun wajar kecewa. Dalam kondisi seperti ini, santri harus kembali menguatkan adab sebelum bicara, akhlak sebelum dakwah, dan ketulusan sebelum popularitas.
Para guru NU mengajarkan agama dengan cinta. Jika cinta itu tidak tercermin dalam perilaku santri, maka dakwah akan kehilangan keindahannya. Ketika santri justru menampilkan sikap kasar, marah-marah, atau merendahkan pihak lain, masyarakat pun bertanya-tanya: apakah nilai pesantren masih terjaga?
Di titik ini, Gus Kautsar tidak membentengi kesalahan. Ia tidak menyalahkan publik. Ia mengajak santri untuk naik kelas dalam kesadaran moral. Dan inilah yang membuat sikapnya terasa sangat berbeda dibandingkan suara-suara lain yang bernada pembelaan buta.
Saatnya Berbenah: Polemik Sebagai Jalan Pulang
Polemik “gus-gusan” seharusnya tidak membuat umat bingung atau saling membenci. Justru, seperti yang diingatkan Gus Kautsar, polemik ini harus menjadi momentum untuk kembali kepada nilai dasar pesantren: tawadhu’, adab, dan keikhlasan.
Santri harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa pondok pesantren bukan pabrik gelar, tetapi tempat penggemblengan jiwa. Bahwa para kiai NU mendidik dengan air mata, doa, dan cinta bukan dengan ambisi viral atau pencitraan semu. Dan yang terpenting, bahwa santri adalah penjaga wajah Islam yang ramah, bukan representasi dari kekeliruan sebagian kecil tokoh muda.
Jika santri mampu menampilkan akhlak itu, kritik publik tidak akan lagi melihat “gus-gusan” sebagai wajah pesantren. Sebaliknya, publik akan kembali percaya bahwa pesantren adalah pusat keilmuan sekaligus pusat keteladanan moral.
Di antara suara-suara yang saling meninggi, Gus Kautsar hadir sebagai penuntun arah. Ia tidak sibuk melawan kritik, tidak tergesa-gesa membela yang keliru, dan tidak jatuh dalam drama digital ala selebritas. Ia memilih jalur kebijaksanaan jalur yang diwariskan para kiai besar NU.
Dan dari jalur itu, ia menitipkan pesan yang sangat relevan:
“Saat santri dicemooh, jangan marah dulu. Tanyakan pada diri sendiri apakah kita sudah menjadi cermin dari cinta dan ketulusan guru-guru kita.”
Sebuah pesan yang bukan hanya untuk santri, tetapi untuk siapa pun yang mengaku murid seorang guru. Sebab muhasabah adalah jalan pulang terbaik bagi siapa pun yang tersesat oleh hiruk pikuk popularitas.