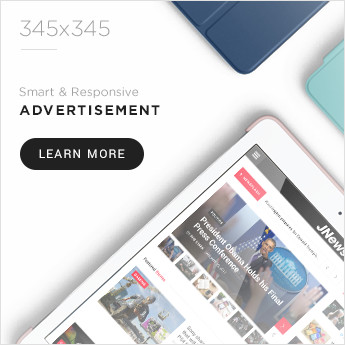Kepulauan Sangihe, gugusan pulau di ujung utara Indonesia, lebih dikenal karena keindahan laut dan budayanya yang kaya. Namun di balik gemuruh ombak dan nyanyian musik bambu, tersembunyi kenyataan sosial yang sering luput dari pembicaraan: kelas sosial. Di Sangihe, sebagaimana di banyak wilayah lain, realitas masyarakat tidak bisa dilepaskan dari struktur kelas yang terus membentuk kehidupan ekonomi, pendidikan, hingga politik.
Dalam konteks ini, teori kelas Karl Marx menjadi alat bantu analisis yang tajam dan relevan. Karl Marx membagi masyarakat menjadi dua kelas utama: borjuis (pemilik modal) dan proletar (kelas pekerja). Meskipun dikembangkan dalam konteks Revolusi Industri Eropa, ide dasar Marx tetap bisa digunakan untuk membaca relasi sosial-ekonomi masyarakat Sangihe hari ini.
Siapa Menguasai Apa?
Di Sangihe, struktur kelas tidak sekadar hadir dalam bentuk pabrik dan buruh. Tapi ia tampil dalam relasi antar mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya (lahan, proyek pemerintah, tambang emas, jaringan birokrasi) dan mereka yang menggantungkan hidup dari laut, pertanian kecil, atau kerja informal.
Kita bisa menyebut kelas borjuis lokal sebagai mereka yang memiliki akses langsung ke kekuasaan baik lewat jabatan birokrasi, kontrol terhadap proyek-proyek pemerintah, maupun hubungan dengan elit politik pusat. Mereka menguasai proyek pembangunan jalan, pelabuhan, hingga distribusi bantuan pemerintah. Dalam istilah Marx, mereka adalah pemilik alat produksi, meski dalam bentuk yang lebih “tropikal”: dana desa, kontrak APBD, dan relasi kuasa.
Sebaliknya, kelas pekerja di Sangihe terdiri dari nelayan tradisional, petani kopra, buruh bangunan, dan tenaga kerja informal yang bekerja tanpa jaminan dan stabilitas. Mereka bekerja keras, tapi hasilnya sering tak sebanding. Laut tempat mereka mencari ikan semakin rusak karena aktivitas kapal besar atau pencemaran, dan harga kopra atau pala sering tak berpihak kepada petani kecil.
Pendidikan dan Mobilitas Sosial
Dalam teori kelas modern, mobilitas sosial adalah salah satu indikator penting. Apakah seseorang dari keluarga nelayan bisa menjadi dokter, guru, atau pengusaha sukses?
Di Sangihe, akses terhadap pendidikan yang baik menjadi penentu utama. Sekolah unggulan masih terkonsentrasi di Tahuna, ibukota kabupaten, sedangkan di pulau-pulau seperti Marore, Kendahe, atau Tabukan Utara, fasilitas pendidikan masih jauh dari ideal. Akibatnya, peluang naik kelas bagi anak-anak di pulau luar inti menjadi sempit.
Marx menyebut bahwa pendidikan dalam sistem kapitalisme sering kali tidak netral—ia menjadi alat reproduksi kelas. Dalam konteks Sangihe, ini tampak dari bagaimana anak-anak dari keluarga PNS, pengusaha, atau pejabat memiliki peluang lebih besar mengakses pendidikan tinggi, dibanding anak dari keluarga nelayan yang kadang harus berhenti sekolah karena biaya.
Kelas Menengah yang Rawan
Kelas menengah di Sangihe terdiri dari guru, pegawai negeri, wiraswasta kecil seringkali menjadi penopang stabilitas sosial. Tapi kelas ini juga sangat rentan. Kenaikan harga bahan pokok, inflasi, dan minimnya lapangan kerja non-pemerintah membuat posisi mereka tidak stabil. Ketergantungan terhadap pemerintah sangat tinggi, sehingga kritik sosial pun sering tumpul.
Dalam perspektif teori Louis Althusser, seorang Marxis strukturalis, lembaga seperti sekolah, gereja, dan birokrasi disebut sebagai Ideological State Apparatus (ISA) alat negara untuk mempertahankan ideologi dominan. Maka tak heran bila kritik terhadap kelas penguasa sering tenggelam dalam wacana “syukur”, “loyalitas”, atau “stabilitas daerah”.
Konflik Kelas dan Kesadaran
Salah satu gagasan utama Marx adalah kesadaran kelas (class consciousness) kesadaran bahwa kelas pekerja memiliki kepentingan yang berbeda dan bertentangan dengan kelas penguasa. Tapi di Sangihe, seperti di banyak wilayah Indonesia, kesadaran ini masih lemah. Identitas etnis, agama, atau keluarga sering lebih dominan daripada identitas kelas.
Namun gejala perubahan mulai muncul. Gerakan masyarakat adat yang menolak tambang emas di Sangihe, misalnya, merupakan bentuk kesadaran yang muncul dari bawah. Penolakan terhadap eksploitasi alam bukan hanya soal lingkungan, tapi juga bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi-politik dari luar.
Dialektika Pulau dan Kelas
Marx menyebut sejarah sebagai pergulatan antara kelas-kelas sosial yang saling bertentangan. Di Sangihe, sejarah ini belum ditulis dalam buku, tapi bisa dibaca dari nelayan yang terpaksa meminjam uang kepada pengepul, dari pemuda yang merantau ke Manado karena tak ada lapangan kerja, atau dari ibu-ibu yang mengelola rumah tangga dengan beras subsidi.
Kelas sosial di Sangihe adalah realitas yang hidup dan dinamis. Ia tidak selalu berbentuk keras seperti di kota-kota industri, tapi justru tersembunyi di balik wajah ramah pulau. Dengan membaca Sangihe lewat teori Marx, kita diajak untuk tidak hanya melihat keindahan alamnya, tapi juga mengerti dinamika kuasa yang menentukan siapa mendapatkan apa, siapa bekerja untuk siapa.