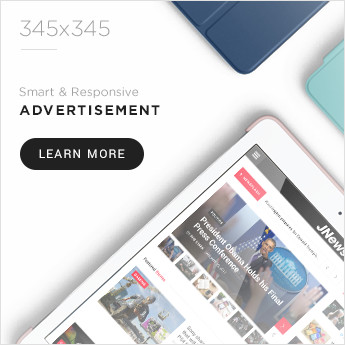Di sebuah ruang sidang yang dingin, di antara tumpukan berkas perkara dan kilatan kamera media, seorang tokoh agama dengan jubah putih duduk di kursi pesakitan. Tangannya yang dulu rajin mengangkat kitab suci kini terbelit borgol besi. Tuduhan? Korupsi dana umat uang yang sejatinya dikumpulkan atas nama sedekah, zakat, atau pembangunan rumah ibadah. Ironisnya, yang terlibat bukan sekadar figur pinggiran, melainkan orang yang sebelumnya dielu-elukan sebagai teladan moral.
Fenomena ini bukan cerita baru. Korupsi yang menyelip di balik simbol kesalehan telah menjadi wajah kelam yang jarang disentuh secara blak-blakan. Kita terlalu sering menganggap agama sebagai benteng moral paling kokoh, sehingga ketika korupsi menyelinap melalui pintu ini, keterkejutannya seperti gempa yang mengguncang keyakinan sosial.
Ketika Agama Menjadi Tameng
Dalam masyarakat religius seperti Indonesia, jubah putih, sorban, dan sebutan “ustaz” atau “kyai” seringkali menjadi jaminan kepercayaan. Di atas mimbar, suara mereka menggelegar menyerukan kejujuran dan amanah. Namun di balik layar, ada yang memanfaatkan kesucian simbol itu untuk menutupi kerakusan.
Para sosiolog menyebut fenomena ini sebagai moral licensing sebuah mekanisme psikologis di mana seseorang merasa memiliki “lisensi moral” untuk berbuat salah karena sebelumnya melakukan sesuatu yang dianggap baik. Dalam konteks ini, reputasi sebagai tokoh agama dijadikan “modal moral” yang ironisnya dipakai untuk melancarkan perbuatan kotor.
Uang Umat yang Jadi Alat Politik dan Gengsi
Kasus dana masjid yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi, atau sumbangan zakat yang dialihkan untuk mendanai kampanye politik, adalah contoh nyata betapa agama bisa dipelintir menjadi alat legitimasi kekuasaan. Korupsi bersarung putih sering beroperasi di ruang abu-abu: tidak ada bukti uang mengalir ke kantong pribadi secara langsung, tapi dana itu dipakai untuk membangun citra, menutup aib, atau membeli pengaruh.
Di sinilah kompleksitasnya: masyarakat kerap ragu mengkritik tokoh agama yang tersandung kasus, karena takut dianggap menghina agama itu sendiri. Padahal, membongkar kasus seperti ini adalah bagian dari menjaga kesucian ajaran.
Bayang-bayang Sejarah dan Peringatan Ulama
Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, “Kerusakan agama disebabkan oleh ulama yang buruk.” Peringatan ini seperti nubuat yang terus relevan. Dalam sejarah Islam, ada kisah para pejabat keagamaan di masa kekhalifahan yang tergoda harta dan jabatan, meski mereka memiliki pengetahuan agama yang luas. Pengetahuan tidak selalu menjamin kesucian hati; kekuasaan dan uang tetaplah ujian yang berat.
Al-Ghazali menekankan bahwa ibadah tanpa kejujuran hati hanyalah ritual kosong. Maka, ketika seseorang berpenampilan alim namun hatinya terikat pada dunia, setiap amalnya bisa saja menjadi sekadar kedok.
Mengapa Masyarakat Mudah Terkecoh?
Jawabannya terletak pada budaya charismatic authority otoritas yang lahir dari karisma pribadi, bukan dari transparansi atau akuntabilitas. Masyarakat kita seringkali lebih percaya pada sosok yang pandai berbicara di mimbar daripada pada data yang dingin. Padahal, karisma tanpa integritas bisa berubah menjadi alat manipulasi yang mematikan.
Kecenderungan ini membuat tokoh agama yang menyalahgunakan kepercayaan sulit tersentuh hukum. Mereka bisa memainkan narasi “kriminalisasi ulama” untuk memutarbalikkan opini publik, sehingga kasus korupsi berubah menjadi isu politis atau sektarian.
Mengembalikan Kesucian dari Panggung Publik
Solusi bukan hanya soal penegakan hukum yang tegas, tapi juga pendidikan publik agar tidak membiarkan agama dipakai sebagai tameng kejahatan. Muhammadiyah, misalnya, melalui berbagai forum resmi menegaskan pentingnya akuntabilitas dana umat dan mendorong pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dengan prinsip good governance. Transparansi laporan keuangan masjid atau lembaga zakat harus menjadi kewajiban, bukan pilihan.
Langkah ini penting untuk membalik persepsi bahwa tokoh agama kebal kritik. Mengkritik perilaku buruk seorang pemuka agama bukanlah serangan terhadap agamanya, melainkan upaya menjaga martabat agama itu sendiri.
Membiarkan korupsi bersarung putih berarti memberi ruang bagi kemunafikan tumbuh subur. Semakin lama dibiarkan, semakin kuat pula keyakinan para pelaku bahwa mereka kebal dari hukum dan kritik. Pada titik ini, agama bukan lagi pembimbing moral, tapi sekadar ornamen yang mempercantik wajah kekuasaan kotor.
Korupsi jenis ini memiliki daya rusak ganda: menghancurkan kepercayaan publik pada lembaga agama dan sekaligus memudarkan semangat kolektif untuk taat pada ajaran moral. Ketika masyarakat mulai berpikir “semua pemuka agama sama saja”, maka keruntuhan sosial sudah di ambang pintu.
Menjaga Iman dari Topeng Kesalehan
Korupsi bersarung putih adalah pengkhianatan ganda terhadap hukum dan terhadap Tuhan. Ia membungkus dosa dengan kain kesucian, menyembunyikan kerakusan di balik doa. Dalam pandangan agama, ini bukan sekadar pelanggaran hukum manusia, tapi juga bentuk kemunafikan yang berat.
Masyarakat religius seperti Indonesia harus berani menatap fakta ini tanpa takut pada simbol atau status. Sebab, menjaga kesucian agama berarti juga membersihkan panggungnya dari para aktor yang bermain dengan kostum kesalehan, tapi naskahnya penuh kebohongan. Karena di akhirat kelak, tak ada sorban atau jubah putih yang bisa menjadi pembela. Yang tersisa hanyalah hati apakah ia benar-benar tulus, atau sekadar bersih di luar tapi busuk di dalam.