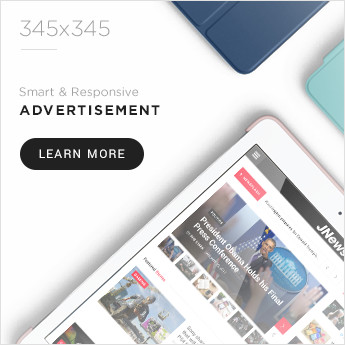Akhir tahun biasanya menjadi momen penuh kegembiraan: pesta pora, kembang api, konvoi kendaraan, reuni keluarga, hingga liburan panjang. Namun, 2025 kita tutup dengan kesedihan yang begitu mendalam bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lain, merenggut nyawa, merusak kampung halaman, serta mengguncang kehidupan ribuan keluarga di berbagai penjuru Nusantara.
Situasi ini memaksa bangsa Indonesia untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertanya: apa makna pesta di tengah duka yang begitu luas?
Saatnya Berpikir Ulang tentang “Pesta Akhir Tahun”
Tradisi merayakan pergantian tahun dengan kembang api dan pesta meriah sudah mengakar kuat di banyak kota besar. Lampu warna-warni, dentuman musik keras, dan kerumunan manusia yang larut dalam euforia biasanya menjadi pemandangan umum. Namun, ketika saudara-saudara kita masih bergulat dengan lumpur, kehilangan tempat tinggal, atau harus bertahan di pengungsian, pesta semacam itu terasa jauh dari hati nurani.
Tidak hanya itu, beberapa daerah bahkan telah mengambil langkah konkret. Pemkot Bogor, misalnya, melarang konvoi dan pesta kembang api pada malam tahun baru sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang sedang berduka. Langkah semacam ini mencerminkan sebuah kesadaran kolektif: ada waktu untuk bersuka ria, tetapi ada pula waktu untuk merenung, berempati, dan berbagi duka.
Pesan Prof. Haedar Nashir: Ajakan untuk Refleksi dan Empati
Di tengah suasana duka nasional ini, Prof. Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menyambut tahun baru dengan refleksi dan empati, bukan sekadar euforia semata. Ia menegaskan bahwa “alam pergantian tahun sepatutnya dimaknai dengan semangat baru, persatuan, dan ketangguhan menghadapi musibah, bukan pesta pora dan kembang api.”
Dalam refleksi akhir tahun bertajuk Bangkit Bersama untuk Indonesia, Haedar Nashir menyampaikan bahwa momen ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperdalam rasa kemanusiaan. Dia mengajak masyarakat untuk mengganti pesta meriah dengan doa, serta memusatkan energi pada dukungan nyata bagi para korban bencana—baik secara moral maupun materiil.
Menurutnya, memulai tahun baru dengan penuh empati dan pengertian terhadap sesama akan menjadikan perjalanan bangsa ke depan lebih produktif dan bermakna. Ia juga menekankan bahwa refleksi spiritual, intelektual, dan sosial adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar perjalanan kebangsaan menuju masa depan yang lebih baik semakin terarah dan tercerahkan.
Doa sebagai Wujud Kepedulian Sosial
Di tengah hiruk-pikuk sosial media dan budaya konsumerisme yang seringkali mendominasi perayaan akhir tahun, suara-suara kebaikan seperti ajakan Prof. Haedar Nashir ini layak didengar lebih luas. Doa bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga bentuk nyata dari rasa kemanusiaan dan solidaritas.
Saat kita mendoakan mereka yang tertimpa musibah baik melalui doa bersama di rumah, majelis taklim, atau instansi Pendidikan kita tidak hanya menunjukkan empati, tetapi juga menjalin ikatan batin sebagai sesama warga bangsa.Doa menguatkan, memberi harapan, dan menjadi bukti bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi bencana dan dampaknya.
Solidaritas dalam Tindakan
Lebih dari sekadar doa, solidaritas juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Banyak organisasi kemanusiaan, termasuk Muhammadiyah, sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, dari pengiriman relawan, bantuan logistik, hingga layanan kesehatan dan pendampingan masyarakat terdampak. Bahkan PP Muhammadiyah menyerahkan bantuan senilai Rp1 miliar untuk korban bencana hidrometeorologi di Aceh, sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam upaya kemanusiaan.
Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara yang sedang mengalami ujian hidup bukan hanya sekadar materi, tetapi juga kepedulian kolektif yang tak tergoyahkan dalam bentuk doa, dukungan moral, serta kebersamaan dalam mengatasi dampak bencana.
Merenung, Tanpa Mengabaikan Kebahagiaan
Mengurangi pesta pora dan kembang api bukan berarti melarang kebahagiaan. Namun dalam konteks saat ini, ajakan untuk merenung sejenak dan lebih memfokuskan perhatian pada mereka yang sedang berjuang dapat membantu kita merayakan pergantian tahun dengan cara yang lebih bermakna dan penuh hikmah.
Ini bukan tentang larangan, tetapi tentang prioritas nilai: antara suka cita individual dan kepedulian kolektif; antara keriuhan pesta dan keheningan doa; antara transformasi kebiasaan dan kedalaman makna. Ketika kita memutuskan untuk lebih banyak mendoakan ketimbang berpesta, kita sebenarnya sedang memperluas ruang kemanusiaan dan empati dalam kehidupan sosial.
Akhir Tahun, Awal Kepedulian
Menutup tahun dengan kesadaran penuh akan kondisi bangsanya berarti membuka pintu untuk perubahan yang lebih besar. Tahun baru 2026 bisa menjadi momentum pembelajaran kolektif bangsa bahwa kebersamaan, ketangguhan, dan empati lebih penting daripada kemeriahan sesaat.
Akhirnya, semoga renungan ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal euforia, tetapi tentang bagaimana kita berbagi ruang hidup dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Dan ketika kepala kita menunduk dalam doa, mungkin di sanalah kita menemukan kekuatan baru untuk bangkit bersama sebagai sebuah bangsa yang besar, penuh belas kasih, dan teguh dalam solidaritas.
Selamat Tahun Baru 2026.
Semoga kita menjadi bangsa yang lebih bijak, lebih peduli, dan lebih satu dalam kehidupan bersama.