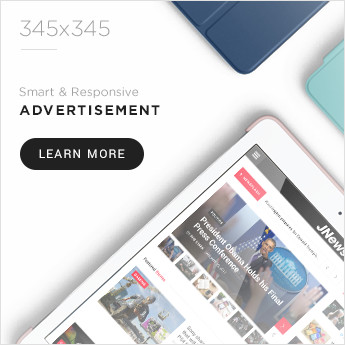Di kota yang dikenal dengan kekayaan kulinernya, aroma ayam goreng renyah tak selalu menghadirkan selera. Belakangan ini, warga Solo dihadapkan pada kenyataan pahit: salah satu warung ayam goreng populer di kawasan Widuran kedapatan menggunakan minyak babi dalam proses pengolahannya. Polemik ini bukan sekadar kasus biasa, namun menyerempet isu sensitif keagamaan dan menyulut kegelisahan publik.
Kasus ini pertama kali terungkap setelah seorang warga melaporkan dugaan ketidakhalalan produk ke pihak kepolisian. Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti setelah pihak warung mengakui penggunaan minyak babi, meskipun selama ini mereka sempat mengklaim kehalalan produknya lewat spanduk dan kemasan yang memuat tulisan “halal”.
Ali Mustofa Akbar, dosen Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum (IIM) Surakarta sekaligus pemerhati isu sosial-politik, mengecam keras tindakan tersebut. “Beberapa pihak telah menyatakan penggunaan label halal pada produk yang mengandung bahan haram merupakan bentuk pembohongan publik dan pelanggaran serius terhadap UU JPH ( Undang-Undang Jaminan Produk Halal). Hal jni juga menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap jaminan produk halal bagi konsumen,” ujarnya dalam wawancara via WhatsApp, Kamis (12/6/2025).
Ia menyoroti lemahnya peran negara dalam menjamin perlindungan produk halal. Padahal, menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, dan barang gunaan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal.
Namun, data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, baru sekitar 4 juta produk yang memiliki sertifikasi halal dari estimasi lebih dari 20 juta produk makanan dan minuman di Indonesia. Celah inilah yang acapkali dimanfaatkan oleh produsen nakal demi keuntungan jangka pendek.
Ali juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak tunduk pada logika ekonomi semata dalam merancang regulasi. “Jangan hanya karena ada kepentingan manfaat pemasukkan negara malah makanan atau minuman yang sejatinya haram justru dilegalkan,” katanya.
Bagi produsen, Akbar menyarankan agar mereka bertanggung jawab secara moral dan hukum. Ia mendorong adanya sertifikasi yang adil, transparan, dan edukatif. “Produsen harus bertanggung jawab atas kehalalan produk mereka. Dan pemerintah juga perlu memperketat regulasi dan sanksi bagi produsen yang melanggar,” tegasnya.
Sementara bagi konsumen, ia mengingatkan pentingnya qiyadah fikriyah (kepemimpinan berpikir) yang membuat seseorang selalu terikat syariat dalam konsumsi makanan. Ia menyayangkan fenomena sebagian umat yang meskipun mengetahui keharaman suatu makanan, tetap menyantapnya tanpa rasa bersalah. “Di samping itu perlu juga ditumbuhkan kesadaran di tengah umat akan wajibnya mengkonsumsi makanan halal bagi muslim,” jelas Ali.
Tak cukup hanya regulasi dan kesadaran individu, ia juga menekankan akan pentingnya kontrol sosial dalam hal ini. “Perlu juga adanya kontrol sosial terhadap sajian makanan di wilayah sekitar oleh berbagai stackholder agar kenyamanan dalam berkuliner bisa diperoleh,” ujarnya. Ia bahkan mendorong terbentuknya forum warga yang memantau kehalalan produk kuliner lokal.
Kasus ayam goreng Widuran seolah menjadi refleksi dari problem sistemik yang lebih besar. Di satu sisi, ada celah regulasi dan lemahnya pengawasan. Di sisi lain, masih minimnya kesadaran konsumen tentang pentingnya kehalalan. Kombinasi ini menciptakan ruang kelabu yang membahayakan integritas produk pangan di Indonesia.
Tak hanya di Solo, kasus serupa juga pernah mencuat di berbagai kota. Pada 2022, sebuah restoran cepat saji di Jakarta Selatan mendapat teguran dari MUI karena menyajikan produk tanpa izin sertifikat halal padahal menggunakan label “halal guaranteed”. Sementara itu, di Surabaya, ditemukan beberapa kedai yang mencampur minyak nabati dengan lemak hewani tanpa menyertakan keterangan di etalase atau kemasan.
Tren ini menunjukkan bahwa masalah kehalalan bukan sekadar persoalan individual, tapi sudah menjadi isu publik yang menyangkut hak konsumen, integritas produk, serta kehormatan agama mayoritas di negeri ini.
Kini, polemik ini menyisakan pelajaran penting. Bahwa kepercayaan publik, sekali rusak, butuh waktu lama untuk dipulihkan. Dan di tengah gemerlap bisnis kuliner yang kian marak, kejujuran dan kehalalan harus menjadi cita rasa utama.