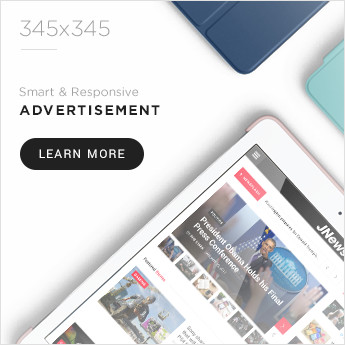Suara riuh tawa anak-anak di sekolah dasar mendadak berubah jadi jeritan panik. Puluhan siswa terkapar di halaman sekolah, sebagian muntah, sebagian pusing, setelah menyantap makan siang gratis dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat itu bukan kejadian tunggal. Sejak awal peluncuran, lebih dari 6.000 anak di 10 provinsi dilaporkan mengalami gejala keracunan massal.
Program yang sejak awal dielu-elukan sebagai “investasi masa depan bangsa” kini justru menghadapi ujian kepercayaan publik. Pertanyaan kunci pun muncul: apakah MBG benar-benar solusi gizi, atau sekadar proyek populis yang tergesa dan mengancam masa depan?
Janji Besar, Realitas Pahit
Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyebut MBG sebagai program kebanggaan pemerintahannya. Targetnya mencengangkan: 82,9 juta penerima mulai dari siswa sekolah dasar hingga ibu hamil. Anggaran awal Rp 71 triliun untuk 2025, melonjak hingga Rp 335 triliun pada 2026, hampir setara dengan 44 persen dari dana pendidikan nasional.
Di atas kertas, ambisi ini terdengar heroik. Indonesia masih bergulat dengan angka stunting tinggi, sekitar 21,5 persen anak balita. Memberikan makanan sehat tiap hari tentu bisa menjadi jalan pintas. Tapi di lapangan, janji itu mudah runtuh. Distribusi tidak merata, menu seadanya, dan kasus keracunan membuat publik bertanya: apakah negara sedang memberi gizi atau memberi racun?
Skandal Wadah dan Higienitas
Selain keracunan, masalah lain menimpa dapur MBG: food tray impor yang dipakai di ribuan sekolah ternyata tidak sesuai standar. YLKI mengungkap banyak wadah menggunakan stainless steel murahan (tipe 201), rawan melepaskan logam berat ke makanan. Ironisnya, sebagian tray tetap diberi label “food grade” dan beredar tanpa sertifikasi SNI.
Di sisi lain, BPOM menemukan dapur MBG sering abai pada standar higienitas. Bahan basi, sayuran layu, hingga daging ayam yang kurang matang menjadi faktor utama banyaknya kasus keracunan. Pemerintah memang sudah menginstruksikan setiap dapur menyimpan sampel makanan selama 48 jam untuk investigasi, tapi apakah langkah reaktif ini cukup?
Anggaran yang Melahap Pendidikan
Bagi banyak pakar pendidikan, masalah paling serius bukan hanya soal keracunan, melainkan soal prioritas nasional. Alokasi Rp 335 triliun untuk MBG tahun depan berarti sebagian besar anggaran pendidikan tersedot ke urusan makan siang.
Padahal konstitusi jelas: minimal 20 persen APBN untuk pendidikan harus digunakan membangun kualitas guru, fasilitas sekolah, kurikulum, dan akses belajar. Bagaimana jika dana raksasa itu justru membuat aspek inti pendidikan terpinggirkan? Seperti kata seorang akademisi, “Anak kenyang tapi bodoh bukan tujuan pendidikan.”
Ketidakadilan di Lapangan
ICW menemukan fakta mengejutkan: beberapa sekolah yang dulu menjadi pilot project MBG justru tidak lagi kebagian saat program meluas. Tidak ada kejelasan kriteria distribusi. Di sekolah luar biasa (SLB), anak-anak difabel diberi menu yang sama dengan siswa reguler, tanpa penyesuaian gizi dan kebutuhan khusus.
Di desa-desa terpencil, dapur MBG kerap tidak beroperasi karena distribusi logistik macet. Ironinya, justru anak-anak di wilayah 3T yang paling membutuhkan asupan bergizi.
Trauma di Bangku Sekolah
Keracunan massal menimbulkan efek psikologis serius. Banyak siswa kini menolak makan dari MBG, meski perut lapar. Di beberapa sekolah, kantin lokal kehilangan pembeli karena orang tua takut mencampur makanan dengan jatah MBG. Bukannya menjadi berkah, MBG justru menghadirkan trauma baru: anak-anak yang seharusnya belajar dengan tenang malah waswas setiap jam makan siang tiba.
Seorang guru di Sukoharjo berkata lirih: “Anak-anak kami jadi takut makan. Mereka lebih memilih tidak makan sama sekali daripada muntah bersama-sama.”
Kritikus menyebut MBG sebagai bentuk populisme gastronomis: program besar yang lebih fokus pada angka penerima dan headline politik ketimbang hasil nyata. Pertanyaan mendasarnya: apakah tujuan program ini benar-benar menurunkan stunting, atau sekadar menunjukkan pemerintah “hadir” di piring rakyat? Hingga kini, belum ada data terbuka yang mengukur dampak MBG terhadap kesehatan gizi. Yang ada justru laporan keracunan dan pembengkakan anggaran.
Menu Perbaikan atau Menu Bencana?
Beberapa jalan keluar sudah diajukan pakar:
- Prioritaskan daerah stunting tinggi, bukan menyebar merata ke kota besar.
- Evaluasi kualitas gizi tiap menu, bukan sekadar jumlah porsi.
- Libatkan UMKM lokal agar dapur lebih dekat, segar, dan memberdayakan ekonomi desa.
- Buka data publik agar masyarakat bisa mengawasi langsung.
- Pastikan anggaran pendidikan tidak terkuras hanya untuk makan siang.
MBG lahir dari niat mulia: menghapus kelaparan, meningkatkan kualitas gizi, menyiapkan generasi emas 2045. Namun eksekusi sembrono bisa menjadikannya bom waktu fiskal dan kesehatan.
Sejarah mencatat, kebijakan populis sering kali manis di awal, tapi pahit di ujung. MBG bisa menjadi tonggak besar bangsa jika berani dibenahi dengan serius: kualitas dijaga, anggaran transparan, dan target tepat sasaran. Tapi jika tidak, ia hanya akan dikenang sebagai proyek raksasa yang memberi porsi gratis hari ini, tapi meninggalkan utang dan trauma esok hari.