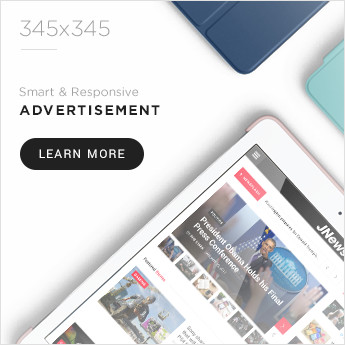Antara Suara dan Hening yang Menyesakkan
Dalam dunia pendidikan, kelas semestinya menjadi tempat lahirnya pertanyaan, bukan sekadar penyampaian jawaban. Namun realitasnya kian kontras: siswa dan mahasiswa berisik saat dijelaskan, tapi diam saat ditanya. Ini bukan sekadar persoalan etika atau disiplin; ini adalah pertanda krisis dalam cara kita belajar dan diajar.
Fenomena ini bisa disebut sebagai paradoks ruang kelas. Saat guru atau dosen menjelaskan, suara-suara dari sudut kelas bergaung, menunjukkan rendahnya keterlibatan aktif. Tapi ketika mereka ditanya, suara itu lenyap; bukan karena pemahaman, tapi karena ketakutan—takut salah, takut terlihat bodoh, atau bahkan takut untuk sekadar bertanya.
Apakah diam adalah tanda paham? Tidak selalu. Bisa jadi, diam adalah bentuk keputusasaan yang sunyi.
Memahami Akar Masalah: Ketakutan, Budaya, dan Persepsi Diri
Untuk memahami paradoks ini, kita perlu menyelami aspek psikologis dan sosiokultural yang membentuk perilaku siswa di kelas.
1. Ketakutan Berbicara di Ruang Publik
Banyak siswa menderita glossophobia—ketakutan berbicara di depan umum. Berdasarkan studi dari Horwitz, Horwitz, & Cope (1986) dalam Foreign Language Classroom Anxiety Scale, ketakutan ini bukan hanya soal bahasa, tetapi juga menyangkut rasa malu, takut gagal, dan takut penilaian sosial. Dalam konteks kelas, ini menjelma jadi diam.
2. Budaya Belajar yang Kaku dan Hierarkis
Di banyak budaya Asia, termasuk Indonesia, guru dianggap sebagai pusat pengetahuan yang mutlak. Ini menciptakan relasi yang hierarkis dan menimbulkan apa yang disebut Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed(1970) sebagai banking model of education—pendidikan sebagai proses “menabung” pengetahuan, bukan eksplorasi. Dalam model ini, murid cenderung pasif karena merasa tak layak atau tak cukup “berhak” bertanya.
3. Fixed Mindset: Takut Salah Adalah Takut Gagal Selamanya
Carol Dweck dalam teorinya tentang mindset (2006) membedakan antara growth mindset dan fixed mindset. Siswa dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan adalah tetap; mereka takut bertanya karena takut terlihat bodoh. Sebaliknya, growth mindset menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Namun sayangnya, budaya belajar kita lebih banyak membentuk fixed mindset sejak awal.
Bukan Hanya Soal Metode, Tapi Ekosistem Belajar
Paradoks ini tidak akan selesai hanya dengan mengganti metode mengajar. Solusinya bukan sekadar pakai teknologi, ice breaking, atau pembelajaran aktif. Yang dibutuhkan adalah perubahan ekosistem berpikir di kelas: dari yang berbasis ketakutan menjadi berbasis keberanian.
Kelas bukan panggung pertunjukan nilai dan gengsi. Kelas adalah taman berpikir, tempat gagal adalah bagian dari pertumbuhan, bukan hukuman sosial.
Menyemai Keberanian Bertanya
Berikut adalah pendekatan solutif yang bisa dilakukan secara subjektif tapi berdasar teori yang kokoh:
1. Mengembangkan Ruang Aman Psikologis (Psychological Safety)
Amy Edmondson (1999) dari Harvard Business School memperkenalkan konsep psychological safety, yaitu kondisi di mana individu merasa aman untuk mengambil risiko interpersonal—termasuk bertanya atau mengakui kesalahan. Guru/dosen perlu secara eksplisit menyatakan bahwa “tidak tahu” bukan kesalahan, tapi titik awal belajar.
Semisal :
- Sambut setiap pertanyaan tanpa menghakimi.
- Beri pujian atas keberanian bertanya, bukan hanya jawaban benar.
- Gunakan humor sehat untuk mencairkan suasana tanpa mempermalukan.
2. Mengganti Model Transfer Pengetahuan dengan Model Dialogis
Mengacu pada Freire (1970), pendidikan harus bersifat dialogis, bukan “mengisi botol kosong”. Guru bukan satu-satunya sumber kebenaran; murid juga punya suara dan pengalaman belajar yang valid.
Semisal:
- Terapkan metode Socratic questioning.
- Buat kelas dalam format diskusi kelompok kecil agar siswa lebih nyaman.
- Gunakan strategi “think-pair-share” untuk mengurangi tekanan publik saat harus berbicara.
3. Melatih Keberanian Berpikir Lewat “Pertanyaan Produktif”
Menurut Vygotsky, pembelajaran efektif terjadi dalam zona perkembangan proksimal (ZPD)—ketika siswa menghadapi tantangan yang sedikit lebih tinggi dari kemampuan mereka, tapi masih bisa dijangkau dengan bantuan. Guru bisa membantu membentuk keberanian ini dengan melatih pertanyaan terbuka.
Semisal :
- Ajak siswa membuat pertanyaan, bukan hanya menjawab soal.
- Gunakan rubric partisipasi yang menilai kualitas pertanyaan, bukan jumlah jawaban.
Refleksi Diri
Siswa perlu diajak mengenali rasa takut mereka. Literasi emosional (Daniel Goleman, Emotional Intelligence, 1995) mengajarkan bahwa mengenali dan mengelola emosi bisa meningkatkan performa kognitif. Sesi refleksi di akhir pelajaran bisa membuka kesadaran bahwa diam mereka bukan solusi, tapi penghambat pembelajaran.
Semisal :
- Akhiri kelas dengan jurnal refleksi: “Apa yang belum saya pahami hari ini?”
- Sediakan “kotak pertanyaan anonim” untuk menampung hal-hal yang tak sempat atau tak berani disampaikan secara langsung.
Suara yang Paling Penting di Kelas
Paradoks ini bukan sekadar masalah perilaku, tapi cerminan dalam dari sistem pendidikan kita yang lebih menghargai hasil daripada proses. Maka tugas kita bukan hanya mendisiplinkan siswa, tetapi membimbing mereka untuk memiliki keberanian paling jujur dalam belajar: keberanian untuk bertanya.
Sebab, edukasi tidak lahir dari hadirnya tubuh semata, tapi dari hadirnya kesadaran dan suara yang mencari. Dan suara yang paling penting di kelas, bukan hanya suara guru, tapi keberanianmu untuk bertanya.