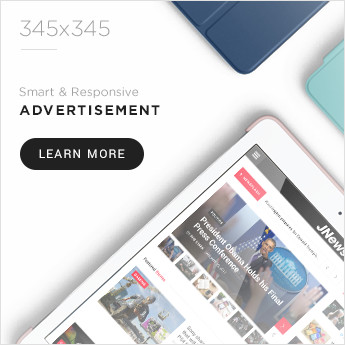Negara Fafafufu
Alkisah, di suatu belahan dunia yang tidak tercatat dalam peta resmi, hiduplah sebuah negara bernama Fafafufu. Negeri ini begitu damai di permukaannya: rakyatnya tersenyum di depan kamera, jalan-jalan beraspal meski tambal sulam, dan pidato-pidato pemimpinnya berisi janji-janji yang berderai seperti hujan awal musim.
Namun, siapa sangka, di balik ketenangan itu, Fafafufu adalah negeri yang tidak ingin rakyatnya pintar. Bukan karena mereka membenci kepintaran. Bukan pula karena rakyatnya malas belajar. Tapi karena pintar itu berbahaya.
Pendidikan yang Membungkam
Di Fafafufu, sekolah bukan tempat berpikir. Ia adalah pabrik seragam—di mana yang berbeda dianggap cacat produksi. Pelajaran bukan alat untuk memahami dunia, melainkan alat untuk menaklukkan ujian. Anak-anak diajari menjawab soal, tapi tidak pernah diajari bertanya.
Mereka hafal Pancasila tapi tidak tahu mengapa sila kelima selalu terasa paling jarang dijumpai. Mereka tahu siapa pahlawan nasional, tapi tak kenal apa arti berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Di negeri ini, berpikir kritis dianggap membangkang, dan bertanya terlalu banyak dilebel “berisik” atau “tidak sopan.”
John Dewey pernah berkata, “Education is not preparation for life; education is life itself.” Tapi di Fafafufu, pendidikan hanya hidup di atas kertas—tanpa napas, tanpa arah.
Media yang Menghipnotis
Jika Plato pernah memperingatkan soal “bayangan” dalam gua yang dianggap kenyataan, maka di Fafafufu, media adalah gua itu sendiri.
Layar-layar kaca dan ponsel dipenuhi dengan gosip selebriti, pertengkaran artis, ramalan bintang, dan sensasi palsu. Sementara kabar soal krisis pangan, kerusakan lingkungan, atau kolapsnya lembaga demokrasi… terkubur dalam algoritma yang tak ramah pada logika.
Mereka tahu, rakyat yang kenyang akan sensasi, tidak lagi lapar pada kebenaran. Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent pernah menguraikan bagaimana media bisa menjadi alat kekuasaan. Dan di Fafafufu, teori ini bukan lagi dugaan—melainkan kenyataan yang sudah dijahit rapi dengan glitter dan musik latar.
Ekonomi yang Membuat Sibuk Bertahan Hidup
“Bagaimana bisa berpikir soal revolusi jika lapar saja belum selesai?” begitulah kira-kira prinsip tak tertulis di negeri ini.
Harga kebutuhan naik, tapi upah nyaris diam. Kebutuhan makin banyak, tapi kesempatan tetap sempit. Warga Fafafufu bekerja dari pagi hingga malam, bukan untuk kaya—tetapi agar besok tetap bisa makan.
Karl Marx, dalam Das Kapital, menulis tentang bagaimana kelas pekerja dijauhkan dari kesadaran kritis karena terjebak dalam siklus bertahan hidup. Maka jangan heran, jika di Fafafufu, rakyatnya lelah berpikir. Bukan tidak mau, tapi tidak sempat.
Ilmu yang Dipinggirkan
Di negara ini, gelar akademik kalah oleh suara mayoritas yang penuh emosi. Fakta bisa dikalahkan oleh opini, dan riset bisa dipatahkan dengan “katanya.”
Ilmuwan, guru, dosen—bukan lagi penjaga kebenaran, melainkan pengganggu narasi yang sudah dipatenkan. Mereka yang bicara berdasarkan data, malah dianggap “sok tahu.” Dan mereka yang bertanya “mengapa” dicurigai punya agenda tersembunyi.
Bahkan Socrates, sang filsuf yang mati karena bertanya terlalu banyak, mungkin akan berkata, “Di Fafafufu, aku lebih cepat dihukum.”
Michel Foucault pernah menyinggung bagaimana pengetahuan dan kekuasaan saling mengunci. Maka di negeri ini, kekuasaan memastikan bahwa pengetahuan hanya boleh beredar sejauh tidak membahayakan status quo.
Kenapa? Karena Rakyat Pintar Itu Sulit Dikendalikan
Rakyat yang pintar akan tahu haknya. Mereka akan bertanya. Mereka akan membaca ulang janji-janji kampanye dan mempertanyakan mengapa tak ditepati. Mereka akan melihat bagaimana korupsi bukan hanya soal uang, tapi pengkhianatan terhadap masa depan.
Mereka akan tahu bahwa pendidikan yang membungkam, media yang memabukkan, ekonomi yang menindas, dan ilmu yang dimatikan… adalah satu kesatuan sistem untuk menciptakan manusia yang tahu diri tapi tidak tahu dunia.
Dan itu menakutkan bagi kekuasaan.
Apakah Ini Hanya Dongeng?
“Ah, untunglah kita tidak tinggal di Fafafufu,” kata seseorang sambil menatap layar ponselnya yang dipenuhi berita viral tak penting. “Kita kan di Indonesia.”
Tapi benarkah ini hanya dongeng? Atau justru dongeng ini terlalu dekat dengan kenyataan hingga kita memilih menyebutnya fiksi?
Fafafufu mungkin tak pernah tercetak di atlas dunia. Tapi ia hidup dalam kebijakan yang membungkam guru, dalam media yang lebih suka rating daripada realitas, dalam sistem yang membuat bertahan hidup menjadi prestasi.
Maka jangan biarkan kita menjadi rakyat Fafafufu. Jangan wariskan ketakutan untuk bertanya. Jangan biasakan anak-anak kita untuk diam hanya karena takut salah.
Seperti yang pernah dikatakan Pramoedya Ananta Toer:
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”
Dan mungkin, selama kita tidak berpikir, tidak bertanya, tidak belajar, maka kita bukan hanya akan hilang dari sejarah—tapi juga dari masa depan.
Semoga ini hanya di negara Fafafufu saja. Dan hanya dongeng semata walaupun diluar sana kita tidak tahu apakah ini kisah nyata atau dongeng semata. Di Indonesia bagaimana menurut kalian para pembaca? Beda donng pastinya..