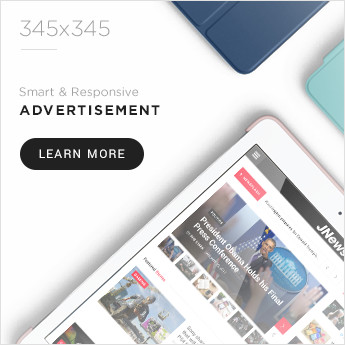Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa dirinya tidak berguna. Bukan karena orang lain secara terang-terangan menghina, tetapi karena suara di dalam kepala terus berbisik bahwa dirinya gagal, kalah, dan tidak layak dicintai. Perasaan ini sering muncul diam-diam, lalu menetap lama, menggerogoti keberanian dan harapan.
Di era media sosial, rasa tak berharga semakin mudah tumbuh. Perbandingan hidup terjadi setiap hari, prestasi orang lain tampil berkilau, sementara luka kita tersembunyi. Akhirnya, banyak orang hidup sambil membawa keyakinan keliru: aku tidak cukup baik. Aku hanya sisa. Aku beban.
Namun Al-Qur’an berdiri berseberangan dengan bisikan itu. Ada jarak besar antara cara manusia menilai diri dan cara Allah memandang manusia. Di sanalah harapan sebenarnya berada.
Low Self-Worth: Luka Psikologis yang Sering Tak Terlihat
Dalam psikologi modern, kondisi ini dikenal sebagai low self-worth. Bukan sekadar rasa minder, melainkan keyakinan mendalam bahwa diri tidak bernilai. Orang dengan low self-worth cenderung merasa keberadaannya tidak penting, mudah merasa bersalah berlebihan, dan sering menyabotase kebahagiaannya sendiri.
Masalahnya, luka ini jarang lahir dari satu peristiwa besar. Ia tumbuh dari pengalaman kecil yang berulang: kritik yang merendahkan, cinta yang bersyarat, kegagalan yang tidak pernah dimaafkan. Perlahan, seseorang belajar menilai dirinya bukan dari siapa ia sebenarnya, tetapi dari seberapa jauh ia memenuhi ekspektasi.
Psikologi mencatat bahwa orang dengan low self-worth sering tetap berfungsi secara sosial. Mereka bekerja, tersenyum, dan tertawa. Namun di dalam, ada suara konstan yang berkata: “Aku tidak cukup.” Suara inilah yang sering disangka kebenaran, padahal ia hanyalah luka.
Ketika Manusia Menghina Diri Sendiri
Ironisnya, banyak manusia lebih kejam pada dirinya sendiri dibanding orang lain. Kita memaafkan kesalahan orang lain, tetapi menghukum diri tanpa ampun. Kesalahan kecil dijadikan bukti bahwa kita gagal sebagai manusia. Masa lalu dijadikan vonis seumur hidup.
Di sinilah masalah eksistensial muncul. Manusia lupa bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh performa semata. Ketika produktivitas turun, ketika gagal memenuhi standar sosial, harga diri ikut runtuh. Padahal manusia bukan mesin prestasi.
Al-Qur’an melihat manusia dengan cara yang sama sekali berbeda. Nilai manusia tidak diukur dari pencapaian, melainkan dari asal-usul dan martabat yang dianugerahkan langsung oleh Allah.
Allah Menegaskan Martabat Manusia
Allah berfirman dengan sangat tegas dalam Surah Al-Isra ayat 70:
“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam…”
Ayat ini tidak bersyarat. Tidak mengatakan “Kami memuliakan yang sukses”, “yang taat sempurna”, atau “yang tanpa luka”. Allah memuliakan manusia karena ia manusia. Karena ia anak Adam. Karena ia diciptakan dengan kehormatan bawaan.
Ini poin penting yang sering dilupakan. Dalam perspektif Qur’an, martabat manusia adalah given, bukan earned. Ia bukan hadiah karena prestasi, tetapi anugerah karena keberadaan. Maka merasa diri sampah sejatinya bertentangan langsung dengan cara Allah memandang ciptaan-Nya.
Bahkan ketika manusia jatuh, nilai dasarnya tidak dicabut. Dosa merusak amal, bukan martabat kemanusiaan.
Adam: Jatuh, Menyesal, Tapi Tidak Dihapus
Kisah Nabi Adam sering disederhanakan sebagai kisah kesalahan. Padahal ia adalah kisah tentang kemanusiaan. Adam berbuat salah, iya. Ia tergoda, iya. Namun Allah tidak menghapusnya dari sejarah, tidak membuangnya sebagai ciptaan gagal.
Sebaliknya, Allah mengajarkan Adam cara bangkit. Adam jatuh, tetapi tidak dipermalukan. Ia menyesal, bertobat, dan tetap diberi peran sebagai khalifah di bumi. Ini pesan besar yang sering terlewat: kesalahan tidak menghapus nilai diri.
Dalam kacamata Qur’an, manusia bukan makhluk yang dituntut sempurna, tetapi makhluk yang diberi ruang kembali. Maka merasa tak berharga karena masa lalu adalah kesimpulan yang tidak Qur’ani.
Mindbook Qur’an: Ketika Ayat Menyentuh Luka yang Diremehkan
Dalam berbagai refleksi Qur’ani yang sering disebut sebagai underrated verses, banyak ayat berbicara tentang luka batin manusia. Ayat-ayat ini jarang dikutip dalam ceramah motivasi, tetapi justru paling relevan dengan krisis harga diri.
Qur’an berkali-kali menegaskan bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher, bahwa Dia mengetahui isi dada, bahwa Dia Maha Lembut terhadap hamba-Nya. Ini bukan sekadar informasi teologis, tetapi terapi eksistensial. Ketika seseorang merasa tidak berarti, Qur’an tidak menyuruhnya “lebih percaya diri”. Qur’an mengajak manusia menggeser sumber nilai: dari penilaian manusia menuju pandangan Tuhan. Di sanalah luka perlahan sembuh.
Low self-worth sering bertahan karena suara internal yang terus berulang. Psikologi menyebutnya inner critic. Qur’an menawarkan inner reminder pengingat batin tentang siapa kita di mata Allah.
Setiap kali suara itu berkata “aku sampah”, Qur’an menjawab “kamu dimuliakan”. Setiap kali batin berkata “aku gagal”, kisah Adam berkata “jatuh bukan akhir”. Ini bukan denial terhadap luka, tetapi koreksi terhadap kebohongan yang kita yakini terlalu lama. Penyembuhan bukan berarti luka hilang seketika. Ia berarti kita berhenti mendefinisikan diri hanya dari luka itu.
Aku Luka, Tapi Aku Tetap Berharga
Merasa tak berharga tidak membuatmu hina. Itu hanya tanda bahwa kamu manusia yang terluka. Yang berbahaya bukan rasa itu, melainkan mempercayainya sebagai kebenaran mutlak.
Allah tidak pernah memanggil manusia dengan label “sampah”. Yang ada adalah hamba, anak Adam, makhluk yang dimuliakan. Bahkan ketika manusia jatuh paling rendah, Allah masih membuka jalan kembali.
Maka jika hari ini kamu merasa kecil, ingatlah satu hal: perasaanmu bisa salah, tetapi firman Allah tidak pernah salah. Dan di mata-Nya, kamu tidak pernah tidak berharga.