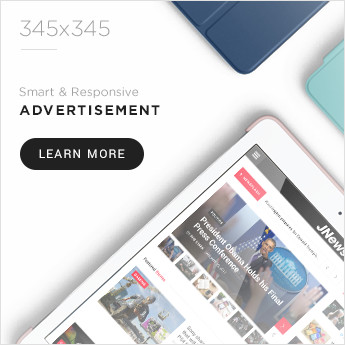Ada masjid megah di tengah kota. Kubahnya menjulang, pengeras suaranya menggema, jamaahnya ramai setiap waktu. Tapi entah mengapa, di antara lantunan doa dan wangi sajadah, terasa ada yang kosong. Sujud dilakukan, tetapi jiwa tak benar-benar tunduk. Tasbih berpindah di tangan, tetapi hati tak bergetar. Di sinilah barangkali letak paradoks spiritual zaman ini: ibadah semakin ramai, tapi ruh semakin sepi.
Fenomena “ritual tanpa ruh” bukanlah isu baru. Ia adalah penyakit lama yang kini menjelma dalam wajah modern: saat ibadah menjadi rutinitas mekanis, dilakukan karena kebiasaan, bukan kesadaran. Kita berpuasa tanpa menahan amarah, berhaji tanpa meninggalkan kesombongan, bersedekah untuk citra, bukan cinta. Kita berdoa setiap hari, tapi lupa berbicara dengan Tuhan dengan hati yang benar-benar hadir.
Di tengah hiruk pikuk dunia digital, ibadah pun sering terjebak dalam budaya “otomatis.” Shalat menjadi checklist harian yang harus diselesaikan cepat, bukan percakapan sakral antara hamba dan Sang Khalik. Dzikir menjadi hitungan angka di aplikasi, bukan aliran kesadaran yang menenangkan batin. Bahkan di bulan suci, seringkali kita lebih sibuk menata jadwal buka puasa daripada menata hati yang seharusnya berpuasa dari kesombongan dan kemarahan.
Ibadah Tanpa Jiwa
Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin pernah menulis bahwa ibadah tanpa niat yang benar hanyalah “gerak tubuh tanpa ruh.” Ia seperti jasad yang berjalan tanpa jiwa. Dalam pandangan sang hujjatul Islam itu, setiap ibadah harus dimulai dari kesadaran hati dari rasa hadir di hadapan Tuhan. Shalat yang benar bukan hanya rukuk dan sujud, melainkan perjalanan batin menuju Tuhan.
Sayangnya, banyak di antara kita lebih menghafal gerakan daripada makna. Kita hafal bacaan, tapi lupa isi. Kita tahu waktu shalat, tapi tidak tahu mengapa kita shalat. Ketika ibadah kehilangan kesadaran, maka ia menjadi kebiasaan sosial alat penanda kesalehan, bukan jalan menuju keikhlasan.
Rasulullah SAW bersabda, “Banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus.” (HR. Ibnu Majah). Hadis ini seperti tamparan halus bagi kita: bahwa ritual tanpa kesadaran hanyalah gerak kosong. Bahwa Allah tidak butuh perut yang lapar, melainkan hati yang tunduk.
Hati yang Hilang Arah
Hilangnya ruh dalam ibadah sering kali berakar dari hati yang lelah. Kita hidup dalam sistem yang menuntut produktivitas, bukan ketenangan. Kita terbiasa mengejar target dunia, tapi lupa mengejar ketenangan batin. Maka, saat beribadah, hati kita tak benar-benar hadir—karena ia masih sibuk menghitung deadline, notifikasi, dan rencana esok hari.
Filsuf Muslim kontemporer, Seyyed Hossein Nasr, menyebut manusia modern sebagai “makhluk terpisah dari pusatnya.” Ia kehilangan orientasi spiritual, sehingga menjalani hidup tanpa arah kosmis. Ibadah pun menjadi rutinitas sosial, bukan perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa berbaris rapi di saf masjid, tapi hati kita tercerai-berai oleh dunia.
Ibadah yang seharusnya menyatukan diri dengan Allah berubah menjadi simbol sosial kesalehan. Kita berlomba-lomba memperlihatkan religiusitas, bukan memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta. Dunia media sosial memperparahnya doa dan amal yang dulu bersifat personal kini bisa menjadi konten. Kita lupa bahwa ibadah sejati tidak butuh penonton, cukup Tuhan sebagai saksi.
Menemukan Kembali Ruh Ibadah
Lalu bagaimana cara menghidupkan kembali ruh dalam ibadah? Kuncinya ada pada muraqabah kesadaran bahwa kita selalu diawasi Allah, dan bahwa setiap gerak kita bernilai di hadapan-Nya. Saat seseorang shalat dengan muraqabah, ia tidak sekadar membaca bacaan, tapi berdialog dengan Tuhannya. Saat ia berzikir, ia tidak sekadar menyebut nama, tapi menghidupkan maknanya dalam hati.
Menghidupkan ruh ibadah juga berarti mengembalikan niat pada sumbernya. Setiap ibadah harus dimulai dengan pertanyaan sederhana: “Untuk siapa aku melakukan ini?” Jika jawabannya bukan Allah, maka kita perlu berhenti sejenak dan menyusun ulang orientasi hati. Karena niat adalah ruh dari segala amal. Tanpa niat yang ikhlas, semua gerak menjadi sia-sia.
Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman, “Maka celakalah bagi orang yang shalat, yaitu mereka yang lalai dari shalatnya.”(QS. Al-Ma’un: 4–5). Yang dimaksud “lalai” bukan orang yang meninggalkan shalat, tapi mereka yang melakukannya tanpa hati, tanpa rasa hadir, tanpa kesadaran akan makna. Betapa banyak kita termasuk di dalamnya beribadah setiap hari, tapi tak pernah benar-benar “bertemu” Tuhan.
Saatnya Kembali ke Hati
Ibadah sejati bukan tentang banyaknya rakaat, panjangnya doa, atau tebalnya kitab. Ia tentang hati yang tulus, mata yang sadar, dan jiwa yang tunduk. Ketika sujud benar-benar menjadi tanda kepasrahan, maka kita akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Karena sesungguhnya, ibadah adalah jalan pulang. Dan setiap shalat, setiap doa, adalah langkah kecil untuk kembali ke rumah asal: kehadiran di sisi Allah.
Mungkin inilah yang perlu kita renungkan hari ini. Bahwa di balik semua kesibukan religius, ada kemungkinan kita kehilangan ruh yang paling esensial. Bahwa dalam keindahan ritus, bisa tersembunyi kehampaan spiritual. Dan bahwa tugas kita bukan sekadar melaksanakan ibadah, tetapi menghidupkannya.
Karena pada akhirnya, Allah tidak melihat seberapa sering kita bersujud, tetapi seberapa dalam hati kita tunduk. Tidak seberapa banyak kita berdzikir, tetapi seberapa lembut hati kita berdialog dengan-Nya. Jika ibadah adalah pertemuan, maka hadirlah sepenuhnya. Jangan biarkan tubuh sujud sementara hati berkelana. Sebab di setiap rukuk yang khusyuk, di setiap doa yang tulus, di sanalah Tuhan menunggu bukan untuk melihat ritual kita, tapi untuk menyentuh ruh kita.